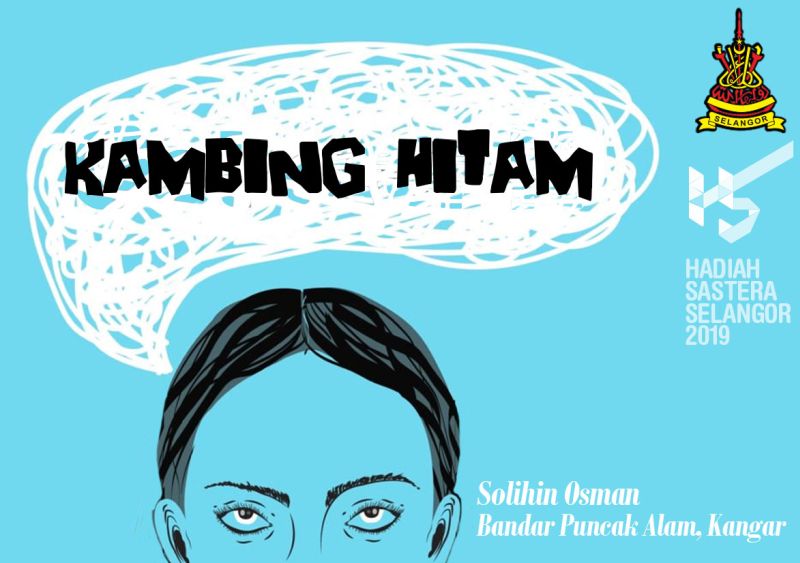Oleh Nik Aidil Mehamad
Jasmin yang kukenal pada satu pagi, tertidur di atas timbunan sayur buruk dalam pasar basah. Aku bawa Jasmin naik ke bilik sewaku yang terletak di atas kedai serbaneka. Aku memapah Jasmin di sepanjang kaki lima bilik-bilik sewa. Di hadapan sebuah bilik, bersebelahan dengan bilik sewaku. Aku berhenti memapah Jasmin kerana Jasmin mengaduh sakit. Kedengaran penghuni dalam bilik sebelah bilikku sedang membakar dadah, bau dadah meresap masuk dari ruang lompong siling bilikku.
Luka-luka di pipi Jasmin dicuci dengan iodin lewat pagi. Darah yang sudah mengering, torehan sepanjang dua inci di bahagian dahi. Sepasang mata yang terpancar kebuntuan meresap masuk ke dalam sepasang mataku apabila mata kami bertentangan. Azan subuh belum habis dilaungkan tukang azan, ingatan kepada Miranda menjelma apabila aku terpandang rambut palsu Miranda yang ditiup angin dari luar bilik. Perasaan janggal mencekik leherku – kewujudan Miranda terasa ada dalam bilik pada waktu itu.
Krismas lagi seminggu, Miranda pulang dan menanti kedatangan Krismas dengan keterujaan yang bertambah pada mulanya. Setiap pagi sebelum Miranda menyalakan rokok dan mengamati burung-burung kecil berterbangan seperti lingkaran ubat nyamuk di balkoni bilik, Miranda akan memangkah kalendar yang digantung di meja solek.
Miranda bangun dari katil, melangkah ke meja solek. Tubuh kurusnya membelakangiku dan aku mengamati kemarahannya yang masih terbaring di katil. Tulang belakang di tubuhnya melayangkan memori yang jauh di kampung halamanku, yang sudah sedekad aku tidak pulang. Bonjolan-bonjolan tulang belakang seperti tar jalan di kampungku, membawa gundah kepada orang-orang tua yang pulang lewat malam dari kedai kopi.
Kemarahan Miranda masih tersisa di pipinya yang kemerahan seperti juga lipstik yang tercalit di bibirnya — menyala. Kataku dengan nada kosong kepada Miranda, “kau lari dari sajak terlalu lama Miranda, lima tahun kau menghilang, tanpa e-mel, nada dering telefon kegemaran kau masih tidak ditukar yang baru, aku menunggu kau dengan ucapan helo yang membahagiakan.”
Miranda masih berdiri di meja solek, di luar bilik aku dengar suara Jasmin – menyanyi dalam bahasa bukan dari bahasa ibundaku. Cahaya matahari masuk dari tingkap bilik membiaskan bayang kurusnya di dinding yang tergantung poster Jim Morisson tidak berbaju.
Miranda tidak lagi menyarungkan rambut palsu kemerahannya. Rambut palsu yang tergantung di cermin solek bertahun-tahun. Selalu juga aku pakainya dan merayau-rayau pada waktu malam. Ada yang memanggilku dengan panggilan nama “Miranda” apabila aku menyarungkan rambut palsunya merayau-rayau di celah-celah lorong bangunan kedai lama pada waktu malam. Sejak itu aku tidak lagi keluar dengan rambut palsu Miranda yang tersarung di kepalaku.
Lima tahun lepas, pada malam Krismas yang tidak diraikan kami — Miranda meninggalkan bilik ini dan juga siang yang dingin ini. Miranda meninggalkan bilik ini lagi. Dia menyarungkan kot labuh berwarna ungu tua dan memulas tombol pintu bilik sebelum berlalu pergi — tanpa ucapan selamat tinggal atau kata-kata baik untukku. Aku tahu kemarahannya kali ini tidak dapat dipujuk dengan alasan apa-apa pun. Kata-kataku seperti gasolin yang menyemarakkan lagi api amarah Miranda- menyala-nyala.
Miranda adalah matematik, logika-logika algebra yang aku jarang ketemu jawapannya ketika di bangku sekolah, namun ia mengasyikkan. Dan tidak lama selepas itu, aku lari dari matematik seperti juga Miranda, lari dari puisi. Kami selalu menghabiskan waktu lapang membaca puisi-puisi Tagore, selalunya pada jam 12 malam ketika penghuni bilik sebelah berdengkur dengan keras. Kata Miranda kepadaku, “Aku dipeluk Tuhan apabila kata-kata Tagore terpancul dari mulutmu, Elena.”
Kedengaran suara perbualan di luar bilik sewaku. Aku bangun dari katil, tubuhku panas, kaki tidak terasa mencecah lantai, bila-bila masa saja tubuhku tersembam ke lantai. Di lubang pintu, aku mengintai Miranda yang sedang memeluk Jasmin di tangga rumah kedai. Dada mereka bergeseran sebelum sebelum Miranda mengundurkan badannya dan melambai kepada Jasmin. Susuknya tidak lagi kelihatan dari mata kiriku yang masih mengintainya dari lubang pintu bilik, sebelum dia berlalu pergi, Miranda menjeling tajam ke muka pintu, seolah-olah dia tahu aku sedang mengintainya di lubang pintu dengan sepasang mata kemerahan.
Mesin-mesin yang merengek dan hentakan kaki manusia yang berkeliaran dalam wad — mencemaskan, bau ubat-ubatan yang menusuk masuk ke dalam rongga hidungku. Aku terbaring di atas katil dan mengamati Jasmin yang berdiri di hadapanku dengan pakaian gimnasitik yang melekat keseluruhan tubuh kecilnya. Antara sela-sela tangisan kedengaran alunan zikir yang tidak kufahami tetapi menenangkan diriku seperti juga bau cadar dan selimut hospital — menemani aku masuk ke dalam mimpi yang baru.
Kata Jasmin, “seperti balasan ke atas kesalahan kau kepada Miranda.” Badanku menggigil, mulutku berbuih. Jasmin membawaku ke hospital dengan menahan sebuah teksi. Jelingan mata pemandu teksi kulihat dari cermin pandang belakang sebelum dia membakar kretek — bau cengkih bertebaran dalam kereta.
Minit-minit terakhirku sebelum aku tidak dapat lagi berkata-kata walaupun satu baris puisi Tagore yang berlegar-legar dalam kepalaku ke telinga Jasmin, yang kudengar dalam kepalaku sekarang suara Miranda, bukanlah suara amarahnya tetapi getaran kata-kata Tagore yang terpancul dari mulutnya selama kami berkongsi hidup. Dan paling melucukan, kami berkongsi rambut palsu, aku gemar dengan rambut palsu kemerahan Miranda dan Miranda pula gemar dengan keunguan rambut palsuku.
Jasmin menari di hadapanku dengan tarian yang mengetarkan jiwa.