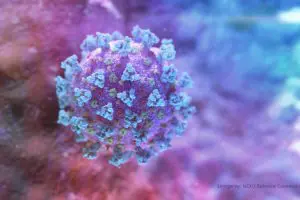Oleh Qurratul ‘Ain
SUARA kepatahan kata-kata. Terbeku. Dia memandang mukanya termangu dalam cermin. Beberapa alat solek tersusun, menunggu dioles pada muka. Tetapi bukankah ini persiapan sebelum memunculkan diri di gelanggang besar sebentar lagi – meredakan duka orang ramai yang dia langsung tak kenali pun (entah para penonton dari lorong hidup yang bagaimana? Tragis? Tertindas?). Kita semua terdesak untuk tertawa supaya kesunyian dibunuh, maka engkau mesti faham kenapa tiket persembahanmu terjual. Ada perasaan gelap meracuni.
Nah, kau antara terpilih mengurangi beban ngeri mereka, pesan guru komedinya, si profesor falsafah politik yang sinikal. Kalau pandang susuk tua ini, mirip gelagat George Carlin bengis dan muram. Namun melalui lelaki tua itulah dia belajar mencintai diri dengan ironi. Petua paling mujarab. Non-sequitur sudah dianuti sebaik-baik habis; bahawa dia tidak usah menjadualkan hari-hari dengan rasa kaku. Cuba melawan jalur nasib dan bebas menarikan hidup! Sergah profesor itu. Tapi parah, sikap pesimistik makin mengada-ngada. Dia meragui kebahagiaan.
“Aneh dan kontra sikapmu,” kata kekasihnya, V, lagi “…dalam curiga maha-panjang itu kau tetap keluar ke pentas mengenakan persona yang melucukan- berharap mereka pulang ke apartmen, wajah berbekas senyuman.” Begitulah percakapan mereka setiap kali bertemu janji di kafe. Kebingungan V tidak pernah berbalas.
Kecuali malam ini, lima belas minit sebelum berpuluh suluhan lampu menyoroti susuknya. Ya, kecuali malam ini, dia mula mempertimbangkan pertanyaan V, kekasih yang tidak sudah-sudah berasa hairan. Ada benar. Dia sangat sukar berasa senang dengan banyak perkara. Orang-orang di sekeliling seperti mendambakan usikan daripadanya supaya mengingatkan mereka, “hei, hidup tak perlu seserius itu,” – tetapi dia juga jarang berseloroh dengan diri sendiri. Pertama kali berjabat tangan teman pelawak di Kuala Lumpur, siapa mampu (atau mahu?) menebak pergelutan takdir pemuda ini.
Apabila memasuki pentas, suatu watak lain terpakai memperdayakan penonton; suatu personaliti yang dia jarang-jarang lihat di bilik solek, acara sofistikated atau di mana-mana mereka kebetulan terserempak. Mata pemuda kemerahan menahan pedih dalam sukma. Terhidu bau ubat terbenam dalam kulit. “Komedi…, datang dari dunia diberati derita, kawanku.” Sejak itu dia tahu, banyak topeng terpaksa terpasang. Menyembunyikan ketulusan.
“Sikapi takdirmu dan jadikan ia jenaka yang mengajakmu cuba bergurau sekejap. Di depan cermin bilik mandi, kau tersengih, peragakan gigimu. Berdamai dengan hati sendiri. Barulah kau memahami bahawa sekian lama ada tawa ingin meledak.” Itulah kali terakhir mereka bersemuka. Pada hari apa, jam berapa; dia sudah lupa, cuma sungguh berbekas pertemuan yang tak ada lanjutannya.
Hampir setahun si pemuda itu berpindah ke kota lain. Dengar-dengar, rambut kusut panjang dan janggut melebat di muka. Mencari-cari makna di kaki bukit. Latih bermeditasi. Entahlah, stereotaip orang yang konon mendapat pencerahan. Konon tentang seorang lelaki yang bertaubat. Barangkali punca perpindahan yang agak radikal ini kerana benar-benar muak dengan mainan populariti. (namun beginikah pengakhiran yang mesti dipuji?)
Dia mencongak kembali niat kerja ini. Bahawa hiburan adalah penawar, semacam antidot sosial. Walaupun dia terpaksa mempersendakan dirinya. Bukankah manusia berkelakar untuk tidak tertipu dengan kelicikan tragedi masa lalu. Seolah kelibat tragedi berusaha menjatuhkan semangat hidup. V lekas memujuk, “si Bassem Yousseff betul bila dia bilang, kau tak boleh ketawakan perkara yang kau takuti. Besar makna itu. Terserah, kalau kau sudah memilih mengekek atau menyeringai pada sesuatu hal —ya, tanda kau berani. Jangan lari dan menjadi pengecut. Pertahankan kenapa kau rasa ada hal yang wajar diperolok-olokkan demi kesedaran yang agung..”
Jari-jari memicit dahi. Gelisah menyendat dalam kepala. Segelas air suam di depan diteguk. Memang memualkan. Segala fobia dan kegagalan dipertaruhkan untuk persona diterima. Sama ada dia pandir yang profesional atau mereka sengaja menguji perwatakannya. “Kau pancing mereka ketawa sehingga tertanya kenapa ia lucu? Pasti, mereka tersentak. Biarkan mereka mempertikai kebersahajaan hidup. Kejahilan. Ketidakpedulian. Sebab ketawa memang jangkitan yang menginsafkan.” Sungguh-sungguh V menenangkan, mengucup ubun-ubun. Dunia berlubuk kepura-puraan. Dia bertambah sangsi. Rasa terganggu. Orang-orang membeli jenaka seperti memburu wahyu. Orang-orang gelak untuk menyedapkan hati yang diabolical. Akhirnya kita terbahak-bahak hingga lupa kitalah si dungu yang sebenar.
“Kau terlalu stoik,”
“Aku ada caraku untuk mendepani semua ini. Menemukan kesenangan dalam kesuntukan nasib dan waktu..”
V mungkin memahami mengapa. Memang, dia setia berpegang pada perkiraan popular ini: percantuman masa dan tragedi menghasilkan komedi. Sebab musibah berlaku pada masa yang tepat, sehingga terpisat-pisat dengan dunia dan candanya yang serius. Dia cuba menenangkan hati yang gelisah dengan mampir ke depan dan bergurau senda. Sesekali dia sengaja membuatkan dirinya tampak jelek. Namun apabila kata-kata diungkapkan menyinggung, ia amat jijik. Seperti harus dibasuh dengan rasa malu yang tebal. Bagaimana teman-teman penghiburnya terbiasa membuat isi dewan menggelegak kejijikan ini? Mungkin mereka mahu menguji siapa lebih bermoral – yang menonton atau yang ditonton? Bingung.
Apabila kebenaran menjadi prop. Seperti ventriloquist dan boneka di tangannya.
Berpendar-pendar. Air yang diteguk habis dan tak terasa puas pula. Dia semakin resah untuk memperkenalkan diri meski sudah berkali-kali dilakukan sebelum malam ini. Sudah tertera nama di poster dan tiket. Dia kurang yakin. Siapa yang sedang dipakaikan dalam badan ini sekarang? Berapa minit lagi? Oh, atau berapa saat berbaki? Jelas dia kehilangan jejak masa dalam jam tangan.
O, kenapa kelohongan ini? Deriaku kian hilang. Persona yang dikekang pesona. Di sana bukankah segala akan berubah maha-sunyi dan bersama suara-suara misteri yang gembira dan penuh cinta? Aku yang tertawa — pasti terdiam pula. O, kekasihku V, pentas menungguku. Ini semua sekadar jenaka. Sekadar. Tidak lebih sebuah perjudian ihsan. Moga kenakalanku halal. Moga aku masih berharga saat dipertontonkan di sana—
Pintu terkuak. Seorang gadis kenit. Staf agaknya.
Lamunan tadi berjejer perlahan.
“Maaf, dah bersedia? Sampai giliran ni.”
“…mereka pun bersedia. Ada luka tak sabar dipadam nanti.”
Staf mengangkat kening sebelum beredar. Seolah mengisyaratkan amaran. Sayup-sayup suara pengacara dan keramaian.
Terasa wajah masih berat melekat dalam cermin.