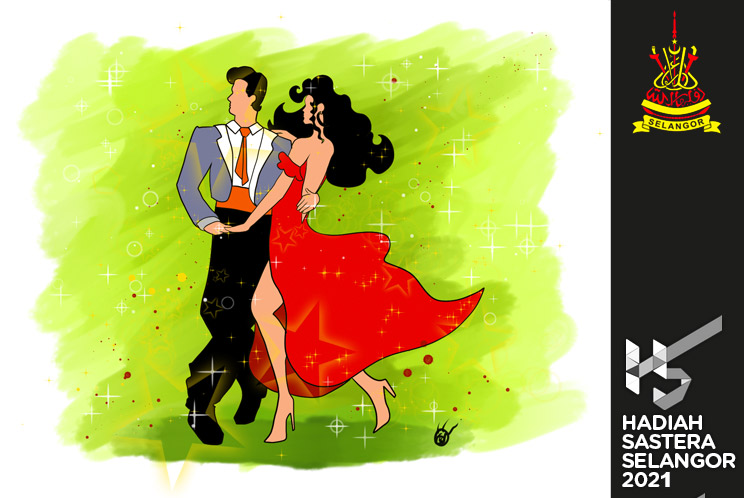Oleh Nur Adila
Ilustrasi Matarojit
Dari Hotel Bel Air, saya mengambil teksi ke Kafe Tortoni. Sejurus tiba, saya mengibarkan tiket dan berbasa-basi dengan pelayan kafe yang ramah di pintu masuk. Saya diiringi masuk ke kafe klasik ala Parisian itu yang diterangi lampu jingga romantik. Kafe ini pernah menjadi La Peña – tempat berkumpulnya para pelukis, pemikir, penulis dan dan ahli filsuf Amerika Selatan sedari dekad 1920-an.
Saya mengetik gambar patung pemikir José Ortega y Gasset dan Jorge Luis Borges yang sedang duduk. “Exactly like it was before,” pelayan muda yang mengiringi tadi begitu lewah mendiskripsi. Saya ke Tortoni untuk menonton persembahan tango. Tidak sah ke Buenos Aires jika tidak menonton tarian tango, bukan? Saya mengajak teman-teman lain – masing-masing diplomat muda dari Turki, Tunisia dan Guatemala – untuk menemani. Tetapi kesemuanya menolak kerana mahu berehat.
Tenaga kami diperah habis petang tadi apabila kami terpaksa turun bas yang pegun sebelum menempuh kerumunan demonstrasi aman besar-besaran di tengah kota Buenos Aires. Pilihan raya umum sudah mampir dan Buenos Aires menyendeng menyokong pakatan politik sedia ada Juntos por el Cambio.
“Bangsa Argentina bangsa ekspresif. Kami selalu punya alasan turun demonstrasi setiap hari. Apatah lagi untuk politik,” German, teman saya dari Kementerian Luar Negeri dan Agama Argentina menerangkan situasi.
“Sí, se puede!”, saya membalas nakal dengan meminjam slogan demonstran ‘Ya, Kita Boleh!’ ala kempen Obama dahulu.
Di Tortoni, saya diberikan tempat duduk paling hadapan dalam dewan gelap itu. Saya terlalu awal. Saya ditanya jika mahu mencicip jus anggur dahulu sementara menunggu.
“Complimentaria,” kira-kira begitu katanya.
Saya menolak dan meminta sedikit espresso. Tidak beberapa lama kemudian, sebelum kopi yang saya pinta tiba, pelayan kafe membawa sepasang lelaki dan wanita – Franc dan Maria – ke meja saya.
“Kalian akan duduk sekali di meja ini untuk persembahan malam ini.”
Masa begitu mewah merahmati kami ruang luas untuk berkenal-kenalan. Franc dan Maria dirasakan seperti teman lama, seperti dua orang ibu dan bapa saudara muda yang begitu melayan anak buah berceloteh di pagi hari raya. Meski Inggerisnya kurang fasih, Maria memaksa lidahnya terus ramah. Dia bercerita: Aku menemani suamiku Franc, jurutera majlis bandar raya Sepanyol yang punya urusan dengan Buenos Aires. Kerana tidak punya anak, Maria mengatakan mereka ‘dimudahkan’ Tuhan untuk terus berbulan madu meski kedua-duanya sudah hampir 50 tahun. Ada sedikit jeda setelahnya. Kami berdua sahaja menawan dunia, katanya sambil mengucil gelak. Franc pula selalu terbabas tema cerita tiba-tiba meminta saya mempertimbangkan cadangannya melawat air terjun raksasa Iguazu di sempadan Argentina-Brazil. Hanya beberapa jam saja dari sini, dan bayangkan kuasa hidroelektriknya! – Franc menambah.
Saya membalas, di malam tango juga mahu bicara hal tenaga dan kejuruteraan? Kami ketawa. Apabila kami bercakap soal status Kafe Tortoni sebagai La Peña, saya dengan teruja menunjuki mereka siri lukisan Juanito Laguna oleh Antonio Berni, seorang pelukis angkatan Neuvo Realismo yang banyak tersimpan dalam telefon saya. Franc bilang dia tahu tentang Antonio Berni dan siri lukisan ini – Berni merakam kapitalisme dan industrialisasi yang begitu menekan Buenos Aires sejak 1950-an melalui pemaparan watak seorang anak lelaki bernama Juanito Laguna.
Pembangunan sewenangnya membaham keadilan ekonomi di negara sosialis ini, saya menokok resah. Di mana-mana juga sama, sambung Maria kesal. Saya tidak sempat menyebut satu lagi watak dalam siri lukisan Berni iaitu watak pelacur, Ramona Montiel. Saya suka watak itu yang mengingatkan saya kepada Salina karangan A Samad Said. Tango adalah budaya yang dihidupkan dunia pelacuran, Maria menokok. Mungkin kepalanya juga sedang terkenangkan Ramona Montiel.
Persembahan tango bermula. Franc dan Maria meneguk jus anggur. Mereka membayarkan satu jar air kosong dan semangkuk kekacang untuk saya. Kami bertukar rasa setelah persembahan tango yang galak itu tamat. Wanita begitu diobjektifikasi dalam tango, saya mengeluarkan topi feminis. Maria ketawa tetapi Franc bersetuju dengan serius. Sejarah memang tak adil pada wanita, katanya, tetapi kita harus bergambar di pentas, sambungnya.
Saya memeluk Maria erat sebelum kami berpisah di luar Kafe Tortoni malam itu. Mereka mengajak saya ke Sepanyol. Saya menjemput mereka ke Malaysia. Kami berjanji mahu saling menghantar khabar. Saya bilang, ah mengapa tujuan pertemuan adalah perpisahan? Mereka ketawa. Maria memeluk saya sekali lagi. Rambut panjangnya lebat dan lembut membenam dahi saya.
Jam sudah terlalu lewat dan mereka berdua ditelan likat malam. Pelayan kafe yang ramah tadi nampaknya menunggu dan mahu menemani saya mendapatkan teksi. Kami di hadapan Kafe Tortoni yang terang-benderang. Pelayan kafe meminta nombor telefon saya. Saya tiba-tiba defensif dan meski 31 jam jauh dari Malaysia, saya menjawab seperti kebanyakan perempuan Melayu: Saya sudah punya suami yang setia menunggu di rumah.
Uber tiba dan bergegas membawa saya pulang ke hotel. Teman-teman lain nampaknya risau saya pulang lewat dan sedang lepak-lepak sambil menanti saya di restoran hotel. Saya seraya bercerita tentang malam tango saya di Kafe Tortoni, dan amigos baru dari Sepanyol kepada teman-teman seperti anak yang galak. Harapnya kalian cemburu, saya mengusik. Teman dari Guatemala mencuit dan bertanya apakah saya mengambil e-mel dan nombor telefon mereka atau vice versa? Ada sedikit jeda setelahnya.
Lebih setahun setelah malam di Argentina, pada satu pagi di Wisma Putra, saya terdetik untuk singgah di bilik seorang teman yang baru pulang dari penugasan tiga tahunnya di Kedutaan Besar Malaysia di Sepanyol. Ketika itu juga, saya dimasukkan dalam Pasukan Petugas Covid-19 untuk kementerian yang antara lain tanggungjawabnya mengumpulkan maklumat status pandemik yang ketika itu paling berleluasa di negara-negara Eropah termasuk Sepanyol.
Saya bertanya pengurusan Covid-19 di Sepanyol. Teman saya hanya mendengus sesal. Katanya – bangsa Eropah hanya menghargai keremajaan dan kemudaan. Menjadi tua adalah merugikan dalam mendapatkan khidmat kesihatan. Apatah lagi ketika Covid-19. Saya pulang ke meja dan membuka galeri gambar telefon bimbit.
Saya mencari wajah dua teman. Saya merindui mereka seperti merindui masakan umi. Emosi tidak bergulir di lidah tetapi begitu mendekam deria hati. Saya berasa kehilangan. Saya berasa mahu menggapai tapi tak sampai. Saya pungguk yang tak akan terbang ke bulan, apatah lagi ke Sepanyol. Moga-moga mereka sihat dan selamat.
Satu hari nanti, moga-moga, saya akan bertemu semula Franc dan Maria, yang selalu menziarahi ingatan dan mimpi saya. Saya mengutus doa kebaikan kepada mereka. Saya mahu mereka terus menikmati ‘kemudahan’ yang Tuhan kurniakan dan terus menawan dunia, seperti mereka menawan nubari (dan penyesalan) saya.