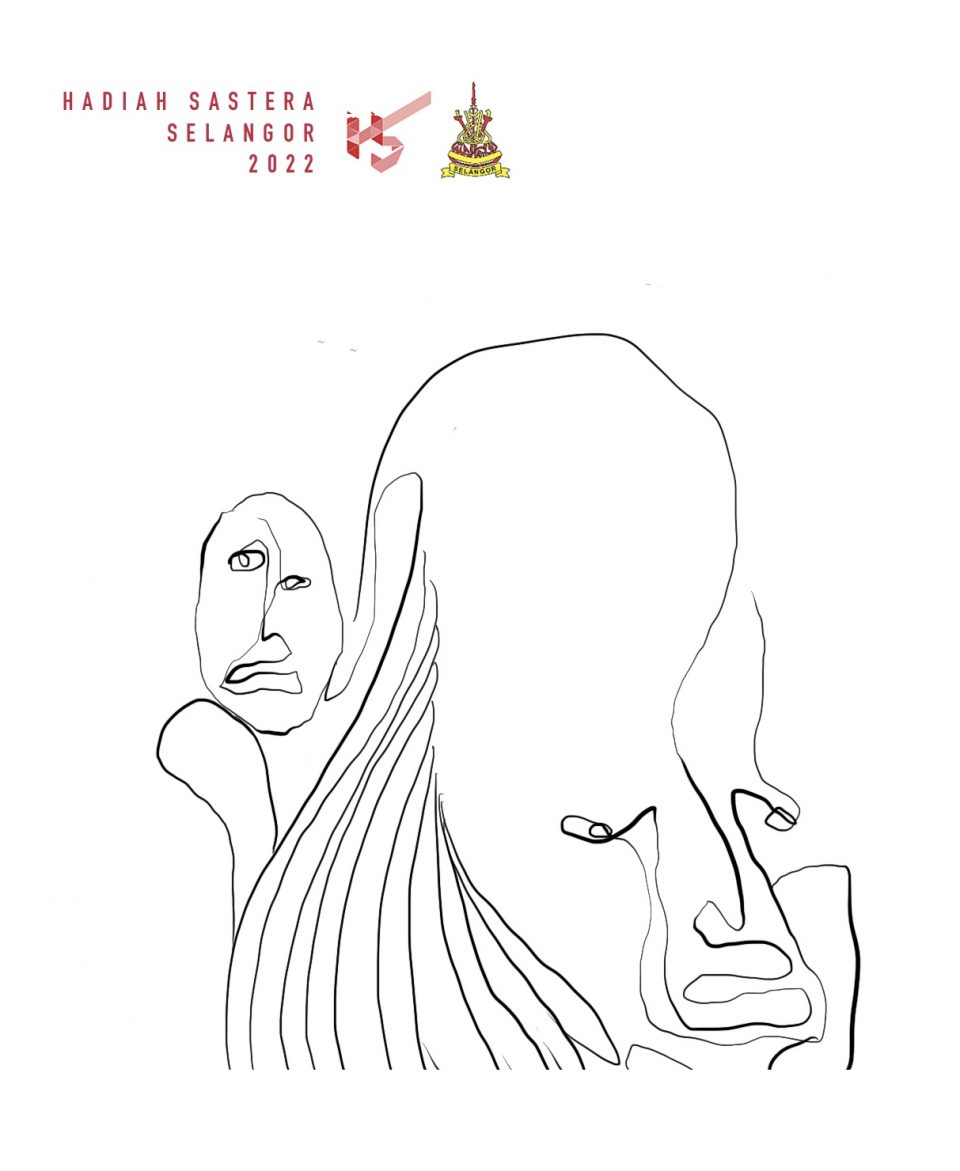Oleh Petak Daud
Dia seorang yang rajin berfikir.
Kerana itulah, setiap kali dia leka melakukan sesuatu: menyapu lantai atau membasuh pinggan, melipat kain atau menanak nasi, bibirnya akan bergerak-gerak seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Adakala, kerut di dahinya mendekat, dan pidatonya pula semakin menguat. Tetapi, apabila menyedari keterlanjuran yang dilakukan mengikut fikirannya, dia akan terdiam sebentar, tersenyum menggeleng kepala dan menyambung semula pekerjaan yang dilakukan.
Apabila kami menaiki kereta bersama-sama (selalunya untuk ke acara-acara seni pada hujung minggu), dia akan memandu tanpa memandang ke kanan dan ke kiri. Sesekali, apabila saya cuba memulakan perbualan, dia tidak akan menyahut, malah terus-menerus memandang ke depan. Ketika melihat dia leka, saya akan menepuk pahanya. Dan dia, begitu jugalah; tersentak dan mengulang-ulang kata maaf sambil meletak tawa pada hujung bibirnya yang kecil.
Saya tidak suka kepada beberapa orang pelajar perempuan di kelas. Apabila dia sedang membaca, kemudian dia hanyut dalam bacaannya, mula menggerakkan bibir dan mengomel-ngomel sesuatu yang tidak didengari sesiapa, mereka – beberapa orang pelajar perempuan di kelas, akan berbisik sesama sendiri sambil tersenyum melihat kelainan yang tidak pernah dilihat mereka.
Tetapi senyuman mereka berbeza. Seperti menghina dan menjijikkan manusia. Jadi, saya tidak suka kepada mereka.
Kerana saya tahu, dia tidak gila. Dia tidak seperti apa yang diceritakan seluruh kampus dari mulut ke mulut. Dia tidak gila. Dia hanya suka membaca, dan selalu terlalu hanyut dalam perasaan-perasaan yang dibayangkannya. Dia tidak gila, dia sekadar lemas, sekadar kesedihan mengenang kematian, dan sekadar kemarahan mengingati penindasan.
Lalu lahirlah kita, yang berada di sebelahnya, yang khusyuk menonton sepanjang cerita.
Kemudian apa yang kita lakukan kepada perkara? Apa yang kita lakukan kepada dia yang sedang tenggelam jauh ke dalam pengalaman emosinya? Apa yang kita lakukan terhadap kanak-kanak yang jatuh dari basikal ketika kali pertama menunggangnya? Apa yang kita lakukan ketika melihat seorang perempuan mengandung sedang berdiri kejung di dalam kereta api yang berhaba? Apa yang kita lakukan, kawan-kawan, sewaktu melihat seorang lelaki tua sedang berjeruk peluh, berusaha untuk sepanjang kudratnya, sekadar melintas sebuah jalan raya?
Kelukaan adalah perkara yang menyedihkan. Adalah perkara yang meninggalkan kesan. Biarpun kau jauh telah sembuh, parut luka yang ternampak akan terus membuat kau sebak.
Tangan saya terketar-ketar ketika ingin meleraikan tali yang terikat ketat di lehernya. Syafik, seorang rakan serumah yang lain, menangis tidak henti-henti di sebelah saya tanpa mengucap apa-apa. Kami berusaha menurunkan mayatnya yang tergantung di kipas siling, dengan lutut longgar dan ucap sabar, yang nyatanya sekadar sebuah penenang untuk diri kami sendiri.
Mulut masyarakat sangat hebat. Cerita berlangsung sangat cepat dan berterusan sehingga melarat. Kematiannya muncul dari pelbagai versi dan spekulasi. Rakan-rakan di kampus masih juga dengan keteguhan pendirian; menganggapnya gila kerana bertindak aneh dan luar biasa di sesetengah masa.
Rakan-rakan serumah, yang kenal benar dengan sikapnya, yang kenal benar akal fikirannya, bersepakat menganggapnya kemurungan. Mungkin kerana ia mendengar kata setiap orang yang mengenalinya.
Kita mungkin terkejut tentang apa yang berlaku. Tetapi, begitulah besarnya kehinaan yang ditumpahkan. Kita mungkin merasa aneh dan hairan tentang apa yang terjadi. Tetapi, begitulah kesakitan yang datang dari mata-mata yang memerhati, dari setiap jumlah mulut yang mengeji. Begitulah, sakitnya masyarakat kita menghadapi perbezaan.
Tetapi, apabila malam datang, setelah kami diam membentang tilam, dia merenung siling yang gelap dan bersungguh-sungguh berkata kepada saya:
“Aku dah maafkan semua,” katanya.
“Aku dah maafkan semua,”
Kerana itulah, saya bersungguh mengatakan seteguh-teguh di dalam hati dan fikiran, bahawasanya ia mati menggantung diri, bukanlah kerana kemurungan dan kesedihan atas apakah yang diperkatakan masyarakat kepadanya. Saya tahu, bagaimanakah fasa pemikirannya.
Kerana setiap kali dia punya masalah yang tidak mampu ditahan-tahankan lagi, dia akan menarik tangan saya tanpa berkata apa-apa, membawa saya ke dalam bilik atau ruang yang tiada orang, lalu kemudian, menangis sehebat-hebatnya.
Dia akan menarik lututnya, menyembab mukanya rapat-rapat ke celahan pahanya, menangis dan terus menangis sehingga penat, dan akhirnya berhenti juga dengan sedu yang lambat. Dan ketika itulah saya akan berada di depannya, bertanyakan berulang-ulang kali, tentang apakah yang telah terjadi.
Biasanya, itu sahajalah fasa emosinya. Kemudian dia akan tersenyum, memandang saya dengan sebuah senyuman yang puas, pipi yang basah, dengan mata yang sembab dan sedu-sedu yang sesekali muncul, dan berkata, tak ada apa-apa.
Tak ada apa-apa.
Saya tidak boleh memaksanya untuk bercerita. Kerana di sesetengah masa, ia menangis terlalu tragis kerana terlampau memikirkan perkara-perkara yang menyedihkan.
Hanya sekali, hanya sekali sahaja, yang ia benar-benar bercerita. Itupun selepas saya berusaha menenangkannya kerana butir perkataannya tidak jelas, dengan sedu-sedu tangisan yang menghibakan.
Ketika itu hari masih pagi, mungkin pukul sembilan, dia naik ke tingkat atas – ke dalam bilik, dan berusaha menenangkan dirinya. Wajahnya ketegangan. Tangannya yang digenggam kuat-kuat seperti menahan sebuah kesakitan, diletakkan lurus-lurus di kedua-dua belah lututnya. Apabila saya bertanya kenapa, barulah mimiknya berubah, barulah ia tiba-tiba tersebak, dan mula berteriak.
Dia mengulang-ulang dengan tangis yang panjang, tentang betapa kita sedang sakit menjadi seorang manusia. Betapa kita terpaksa menjualkan segalanya demi perkara yang sekadar kepentingan kita. Ia menangis dan menangis tanpa henti, bercerita tentang berita yang telah dibaca, tentang seorang anak kecil yang dirogol entah oleh siapa, dan dibuang sesuka-suka di mana-mana. Dia menangis menggoncang tubuh saya, membayangkan dirinya adalah kanak-kanak itu, menunggu setiap kesakitan, menanti setiap jarah kematian yang bakal berkesudahan. Dia menangis membayangkan bagaimana kanak-kanak itu adalah adiknya, adalah kakaknya, adalah ibunya, adalah manusia-manusia kesayangannya.
Apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, katanya.
Apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat, apa aku nak buat.
Tetapi, walaupun begitulah ia berkelakuan, apabila malam datang, setelah kami diam membentang tilam, dia akan merenung siling yang gelap dan bersungguh-sungguh berkata kepada saya, bahawa,
“Aku dah maafkan semua,” katanya.
“Aku dah maafkan semua,”
Kerana itulah, saya bersungguh mengatakan seteguh-teguh di dalam hati dan fikiran, bahawasanya dia mati menggantung diri, bukanlah kerana kemurungan dan kesedihan atas apakah yang diperkatakan masyarakat kepadanya.
Ada perkara yang lebih besar, yang patut kita fikirkan. Tetapi yang remeh-temeh itulah senantiasa benar, menghalang perbuatan.