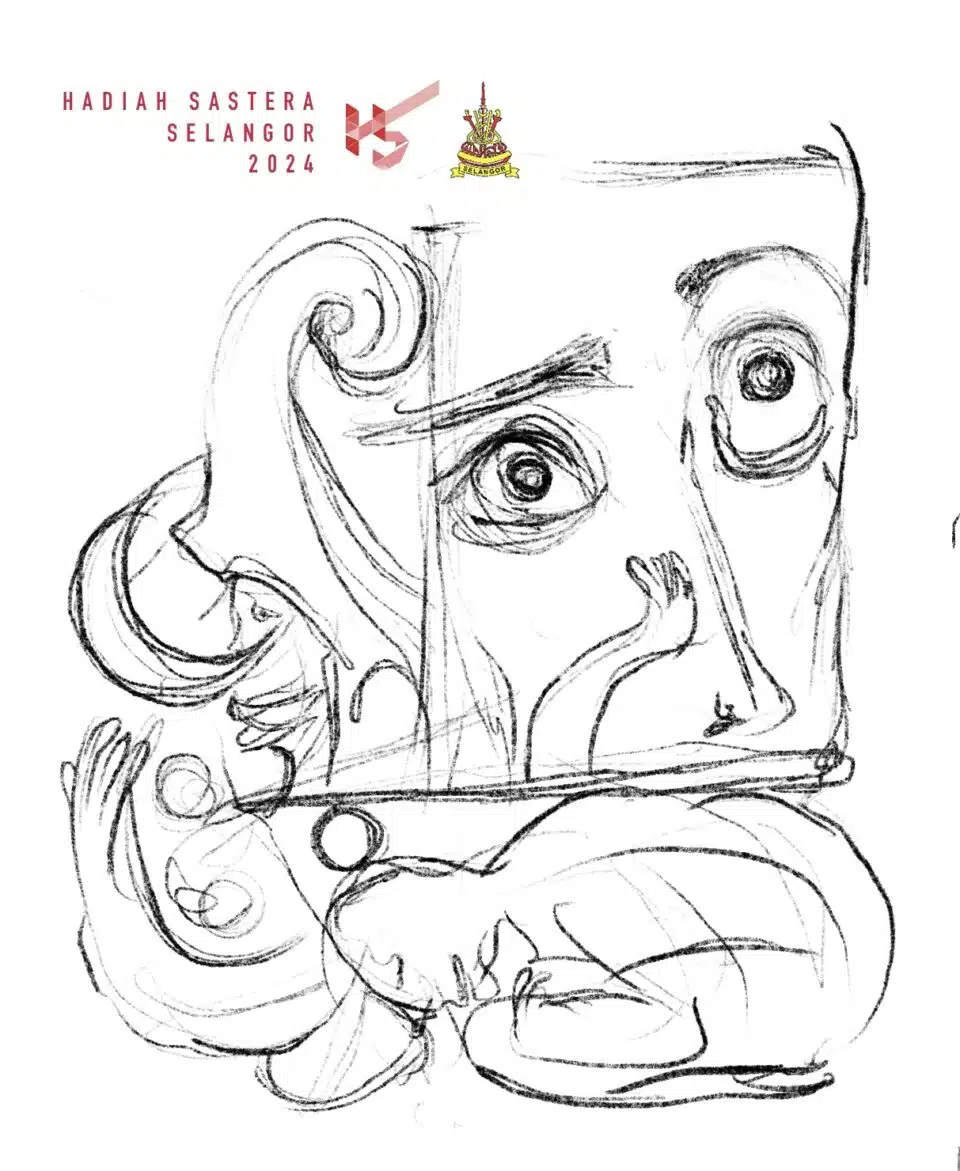Oleh Jaya Ramba
Aku sekali lagi sedar daripada mimpi ngeri. Bukan mudah mahu aku katakan. Kisahnya dari utara hingga ke selatan dan daripada sebuah negara bersultan sehingga menjadi sebuah daerah kecil buangan. Daerah ini kononnya sebagai hadiah kepada penjajah.
Etnik di pulau ini adalah bangsa bertamadun. Mereka masyarakat yang diasap awan amalan dan adat keturunan. Mereka mencipta sebuah syurga rimba yang didiami sang dewa. Sang Dewa ini antara makhluk terhebat tetapi tanpa identiti. Mereka telah membentuk sebuah tamadun yang berjaya dengan sistem penuh pantang-larang. Mereka etnik kecil yang cukup agung. Lalu, terikat sebuah janji bernama sumpahan dari langit ke tanah.
Mereka ini pemuja yang percaya akan lautan, sungai, tanah dan langit. Mereka dewa rimba yang boleh berubah menjadi makhluk apa sahaja. Mereka sangat mulia dengan pantang-larang yang dijaga. Mereka menggelarkan sebuah empayar bersempadan dengan nama bumi “ngayau kepala”. Mereka memecahkan etnik keturunan merujuk kepada daerah rendah, bukit, gunung, sungai dan lautan. Etnik ini mengamalkan cara pembahagian perbatasan rapi dengan kekuatan pada sistem kuasa ditetapkan. Mereka mengamalkan sistem kehidupan yang dipengaruhi tanah, langit, sungai, dan lautan. Tangkal inilah janji alam. Mereka memerintah empayar rimba tanpa raja tetapi rimba berkenaan akan berubah di atas satu kerajaan.
Penyelesaian ini tidak boleh dilakukan sebarang. Tetapi harus dengan kembali ke zaman silam. Harus ditemui “petunjuk” yang boleh mengubah masa. Maka, aku ingat rumah panjang asal yang bapa pernah gambarkan. Aku juga ingat rumah panjang moden yang pernah didatangi lima tahun lalu. Begini kisahnya.
Entah, bagaimana aku berada di perbatasan ini. Ramai orang duduk di ruai. Di beranda juga tidak mudah dihitung jumlahnya. Aku berdiri tanpa dipedulikan. Aku berlalu menghampiri barisan tokoh upacara. Dua tiga orang tua berpengaruh menggeleng-geleng kepala ketika membaca hati khinzir yang berdarah.
“Hati khinzir! Tidak baik!” Akhirnya seorang tokoh berpengaruh bersuara. Mereka sedar apa yang dikatakan.
Air sungai di hadapan rumah panjang ini mengalir lesu ketika kegelapan menguasai alam. Inilah kunci alam. Di sini saudara aku ditunang oleh alam ketika upacara mendulang tulang dulu. Aku sedar rupa-rupanya aku juga diuji.
Aku telah merantau ke banyak daerah yang dikatakan pertapaan panjang demi hidup mati bangsa kami. Ini kemahuan masa depan. Bukan mudah perbatasan dibuka kerana kunci laluan adalah sumpah. Aku tidak temukan jalan terakhir. Aku ditebat petir tongkat martabat. Hari ini sekali lagi perjalanan yang panjang diharungi.
Setelah menempuhi seribu liku, mengharungi halangan dan rintangan sukar. Setelah melalui detik seram menakutkan. Setelah semuanya diperoleh fikir matang, dikunyah kenyang menjadi pengalaman, ditimbun takungan hati, digenggam erat segala hajat dan dipadu akar ilmu. Adalah engkau memiliki kunci petunjuk itu? Detik ini hanya perlu diakhiri dengan nyanyian keramat. Tongkat martabat keturunan itulah jawapannya.
Aku ingat pada mimpi malam tadi. Aku yakin berada di rumah panjang ini. Datuk mengusik Dom yang kelihatan tenang. Nama Dom telah ditukar dalam upacara semalam. Aku pula perlu mencari identiti diri sehingga aku boleh menyentuh hati alam.
Aku memerhati tiang kelingkang. Di sepanjang setiap ruai juga serupa. Tikar berukiran menghias sepanjang ruai. Ketika ini, lapan orang tokoh sudah bersedia. Aku baru selesai menyarung pakaian tradisi ketika kegelapan membungkus alam.
Lalu, mereka tiba-tiba bangkit, menuju ke arah aku. Aku pula melangkah ke hujung ruai. Aku melihat pintu di hujung ruai terkuak perlahan-lahan dengan angin bertiup nyaman. Aku sudah bersedia sepenuhnya.
“Aku buka gerabak zaman, terkuak pintu silam. Aku hamparkan tikar bembam, duduk engkau semalaman. Aku melangkah ke titian, sampai ke sudut kayangan. Aku hayun pedang ilang, terpacak di dinding larangan. Aku robohkan tembok usang, dibangunkan menara impian. Aku jejak laluan silam, untuk pacakkan menara harapan. Aku harungi dalam nanga sungai, untuk nyalakan cahaya. Aku sampai ke kuala, meleraikan tambatan petaka. Aku mahu naik ke bukit, memetik bunga di puncak langit. Aku tidak takut jurang, kami boleh terbang. Aku tidak takutkan gaung, kami kental bertarung. Aku sudah datang, dengan pedang matang. Aku sudah tampil, dengan senjata fikir. Aku di sini, dengan kunci pasti. Akukah yang engkau bina…” Telingaku mendengar ayat-ayat yang mulutku seru.
Tokoh adat yang berada di belakang aku menyelat dengan bahasa kuasa sokongan. Mereka tekun di belakang aku, mengikut turutan angin yang bertiup. Aku tahu mereka hadir. Mereka alam malam yang seram. Mereka menurut erti sinaran bulan. Kami telah berjaya menempuhi derasnya air sungai dan menepis semua rintangan yang datang.
“Malam kian ke depan, membuka pintu siang. Bulan membakar awan, bintang-bintang ketawa riang. Rimba ini berlarangan, aku goncang gunung berjurang, sungai tanpa nanga, tebing tanpa kuala. Aku melangkah, semua diredah. Buka pintu itu, aku masuk dulu. Aku bawa aman, terangkan laluan. Aku bawa damai, terangkan denai. Aku bawa janji, lenyapkan benci. Aku bawa tangkal, buka pintu sangkar.” Aku terus melurukan bahasa kata jiwa.
Aku terus melangkah gagah dengan hati damai. Para tokoh mantera pula menepis angin, menyisih bayangan yang menjelma dan menepis usikan yang cuba membantutkan langkah kami. Kami hampir merentasi dunia sebayan. Aku dihulur segelas tapai apabila melintas setiap bilik di ruai. Aku langsung masukkan ke mulut. Aku sedar yang aku perentas malam menuju ke gagang pagi.
“Cucuku! Cucu makhluk yang cukup hebat!” Aku mendengar bisikan datuk yang aku renung dari jauh.
Ketika ini aku merasa sedang melalui pintu sempadan dengan laungan damai. Pengikut aku juga turut diberi tepukan yang menggamatkan. Bagaikan aku berada di ruai tetapi aku sedar, aku di tempat asing yang lain. Aku terus bermantera dengan tongkat yang dipegang kukuh. Di satu sudut yang cukup samar, aku melihat bayangan mengintai. Endun Bulan yang menjadi penentu sebuah harapan.
“Inilah jiwa engkau. Roh. Inilah petunjuknya!” Ujar Endun Bulan berbisik di telingaku.