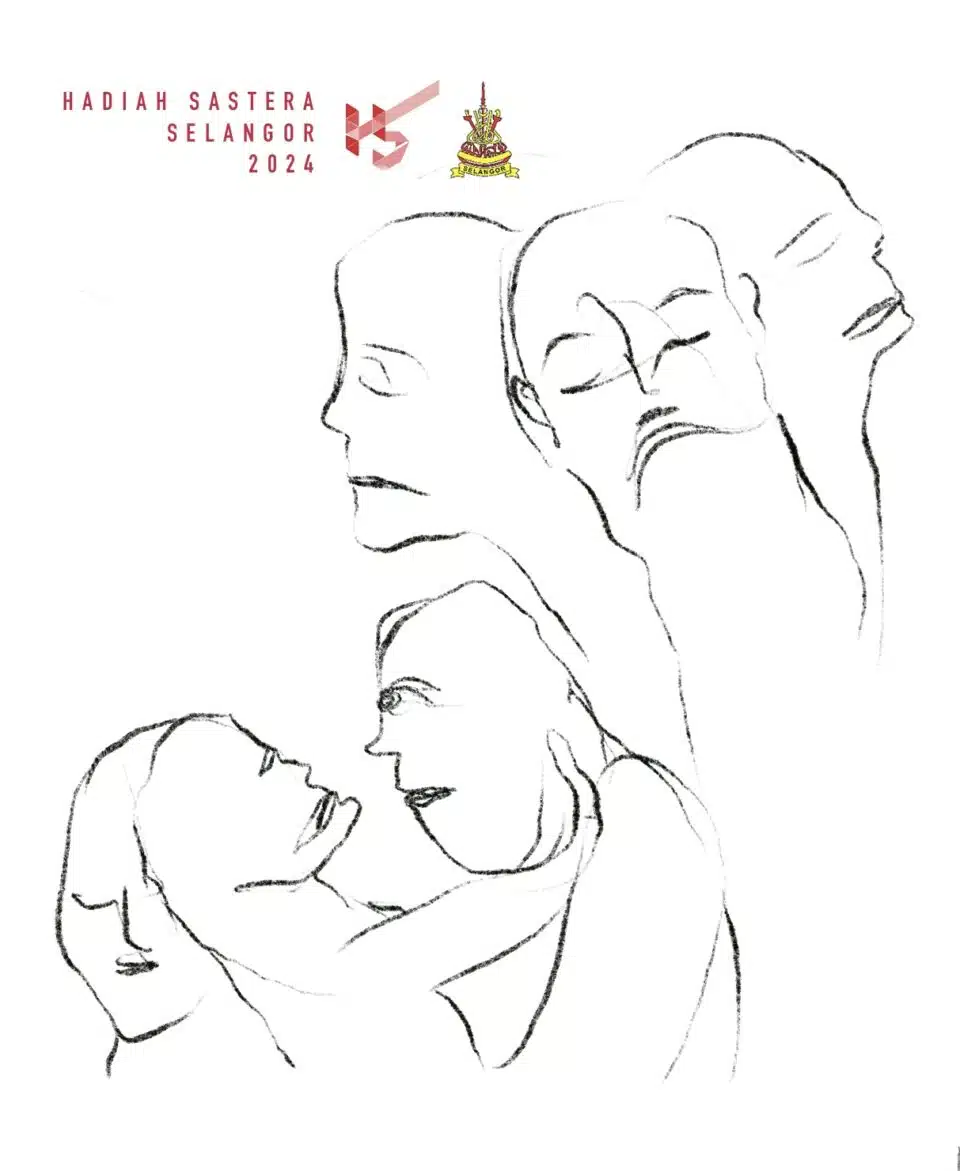Oleh Daeng Ramliakil
Sesungguhnya berada di suatu daerah perbukitan dan banjaran itu, aku tak pula berasa kekurangan berlebihan atas pemberian Allah SWT. Diajar nenekku, atau kupanggil wek, sesuai dengan budaya warisan Istana Pagaruyung, Allah SWT itu memerintah ruh dan jasad, suatu penafsiran dan pemahaman yang menjadi amalan seharian, yang berbeza ketimbang pakaian harian golongan yang memilih syariat bersendikan kitabullah yang dipakai sejumlah besar ustaz bani ciku, sejak 1,000 tahun. Berada di puncak-puncak bukit, sesekali tiba juga suara yang kejauhan. Dua suara, lagu dendangan seseorang yang sudah pernah kudengar dan bunyi petikan gitar tunggal.
Aku amati. Suara itu tiba lagi.
Tak sukar fahami maksud penyuara. Sebalik bait dan kata dendangan Yulisa yang setahuku, adik lelakinya Ilyas si pemetik gitar, hati terasa teramat sayu, hingga tergambar wekku yang sekitar 200 tahun lalu, berusia 10 tahun sertai rombongan 200 orang dewasa dan sejumlah kecil kanak-kanak, berjalan kaki dari Istana Pagaruyung, yang ada ketikanya, menunggang gajah-gajah yang dibekalkan. Menyeberang selat, bahtera buatan bani ciku.
Kesenyapan alam daripada terhentinya dendangan lagu, lelaki itu memasang easel dan meletakkan kanvas yang sudah diregang pada bingkai, yang pada ukuran 3’x4’ itu, dia berasa selesa menggambarkan rupa perasaannya. Kalbunya bisik, sesuai dengan kata-kata adiguruku, Pablo Picasso, kerja-kerja menggambarkan bermula dengan kehendak kalbu, lantas terus menggambar dan berhenti setelah kalbu nyatakan begitu.
Sesudah kira-kira suatu ketika mata lelaki itu melihat arlogi di lengan kiri, hati ketahui lalu bisik, ‘sudah 33 minit berlalunya waktu’. Dia berasa hatinya sudah pilih titik henti.
Gambaran apakah ini?
Rombongan sejumlah manusia yang berbondongan melalui laluan yang di kanan kiri, pohonan yang tidak asing kepada siapa pun yang hidup di daerah Istana Pagaruyung itu pada hujung abad ke-17. Kesemuanya pohon buah-buahan baik yang manis mahupun yang kelat sedikit, termasuk kelubi dan salak.
Entah mengapa, waktu lelaki itu merenung gambaran di atas kanvas itu, sekali lagi lagu tiba ke telinganya.
Terasa tidak jauh antara maksud lagu dengan gambaran kalbuku yang sudah pun mendarat di landasan kanvas ini. Bisik kalbu lelaki itu.
Tanpa henti lama, lelaki itu tergiur untuk melihat gambaran kedua kalbunya.
Kanvas baru, saiz sama, diguna terus palette knife lantas cat-cat minyak aneka warna dicalit-calit. Diratakan. Ditompok-tompok.
Jadi apa ini?
Dia ingat pada teori-teori. Dia ngerti, tak semestinya teori itu perlu. Namun, bisik hatinya, ingatan pada beberapa teori Zhangwil, teori estetika jadikan ia penampan sendaan, ejekan dan umpatan sejumlah malah ramai individu yang tidak bersekolah, lantas hilang akal-ilmu.
Selang 33 minit lagi, kalbunya beri isyarat berhenti.
Dia amati gambaran baru.
Hatinya terkata-kata. Inikah rupa wajah-wajah bani ini, yang nyata, ia berupa gambaran dari gua dalam jasad masa.
Tak terasa aneh. Kendati hodoh, namun andai ini realiti, apakan daya. Harus terima. Hati tak menipu. Akal mampu kerana pilihan logik bertujuan kononnya lebih bagus. Hati tetap dengan caranya yang berkejujuran.
Selarikah gambaran kedua ini dengan maksud lagu?
Lelaki itu tertanya-tanya. Dicapainya sebatang rokok untuk dipanciskan. Tiba-tiba, tersedar dia. Diperhati, kemudian dilemparnya ke kejauhan ke lembah. Dia tahu, rokok ciptaan Zionis itu racun pembunuh paru-paru triliunan manusia sejak Perang Dunia Pertama.
Lelaki itu keluarkan botol air zam-zam. Jernih bisiknya. Lantas, dengan Bismillahirahmanirrahim dan Alhamdulillah, dia meneguk sopan tiga kali.
Beginilah jadi bani Melayu atau Jawi, panggilan bani Arab. Bisik hatinya sambil mengusap dahi yang mula berkeringat.
Lelaki itu terjongkok-jongkok mengamati pohon renek yang kalau-kalau ada menghasilkan bunga seumpama bunga senduduk. Nah, kata hatinya, itu pun.
Dia petik, amati kebersihan dan dikunyah bunga-bunga itu.
Pucuk-pucuk kayu di situ turut dipetik dan dikunyah.