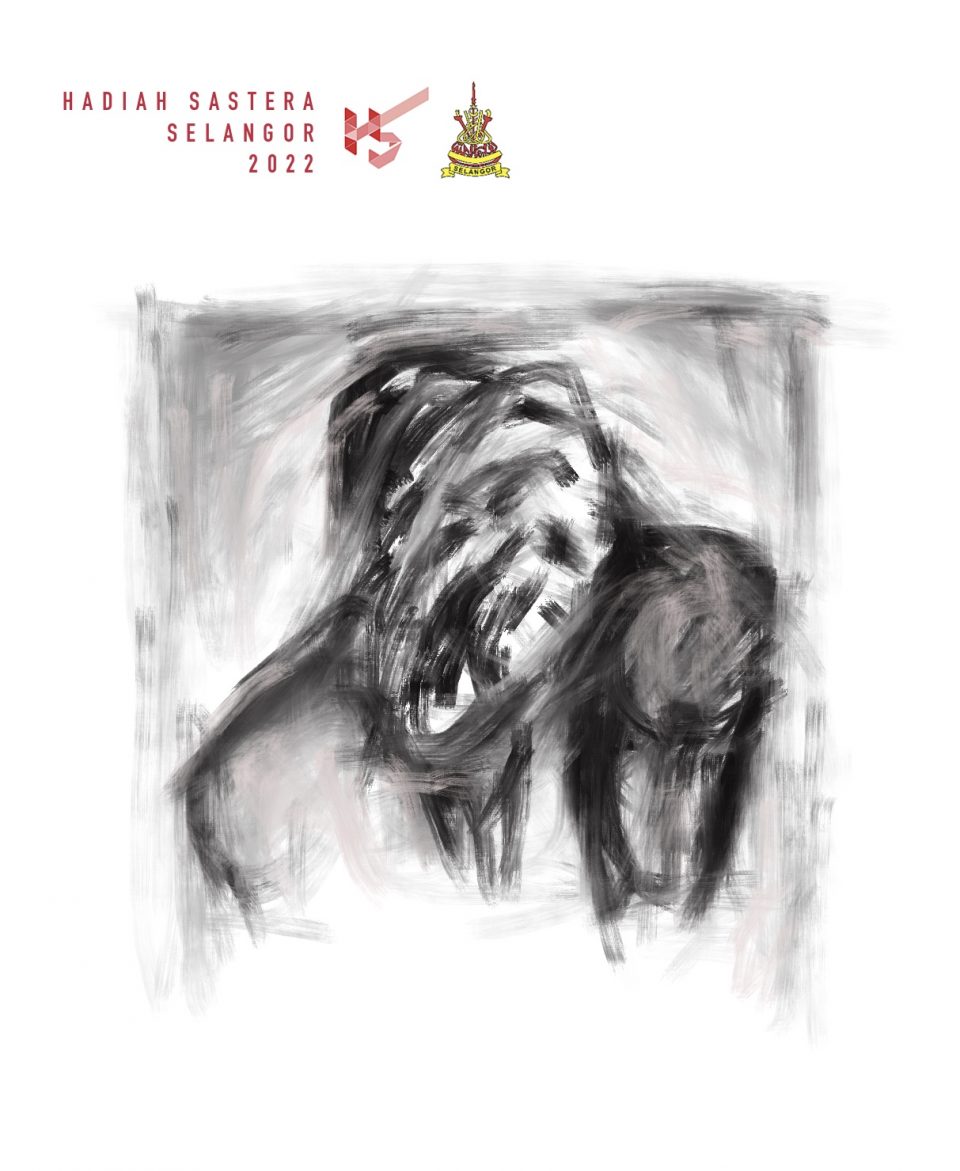Oleh Qurratul ‘Ain
Dalam esei Johan Radzi, Bung Pram, penjara dan kemaafan, siaran Selangorkini tahun-tahun lalu, Johan menyitir Jacques Derrida: “Apabila sesuatu itu boleh dimaafkan, maka ia bukanlah satu kemaafan.” Kemudian dia simpulkan begini: “jika Kemaafan Mutlak tidak wujud dan kita takkan dapat mengecapinya, maka apa lagi yang kudus di dunia yang bergelumang dengan sengsara dan penuh fana ini?”
Apa Johan Radzi tegaskan, bukanlah baharu; kemaafan diperkatakan memang lama. Aristotle, pemikir popular ini membawa nilai sungnōmē (konsep memiripi kemaafan dan belas-ihsan). Walaupun Johan Radzi mengulangi apa pengarang-pengarang terdahulu bahaskan, ia mesti diulang-ingatkan kerana kemaafan sentiasa wujud pada setiap keadaan yang tidak terinsafkan. Kemaafan didasari oleh penguasaan dan keberuntungan yang ingin dipunyai.
Tetapi dalam memperihalkan kemaafan ini, saya lebih cenderung memahami paradoks dan kerumitannya dengan mengulang baca kisah Adam dan Hawa. Dalam naratif ini, segala sisi manusia asas terhimpun pada suatu detik peristiwa. Dari penasaran yang polos hingga kesalahan yang ranum. Adam dan Hawa mengizinkan diri mereka melakukan tindak terlarang dalam syurga, ingin meneroka nafsu – yang saya fikir agak ironi kerana ia berlaku di tempat yang mulia. Ia semisal bersetubuh di dalam masjid atau gereja. Mereka melakukan dosa di tempat Tuhan redhai, tempat kita cucu-cicitnya ingin kembali huni. Peristiwa ini memunculkan persoalan Kemaafan antara manusia dan Tuhan.
Adam dan Hawa, setelah berdosa, adakah rasa kemaafan terlintas dalam fikiran mereka tanpa perlu diajarkan? Adakah kemaafan ialah sifat automatik, diprogramkan tanpa panduan? Sewaktu mereka tengadah dalam kekesalan yang memberat setelah menggigit khuldi yang sepatutnya mereka musuhi, adakah mereka menyedari sebuah kemaafan menjalar dalam diri? Suatu emosi, suatu perasaan baharu dipelajari. Mereka tidak tahu apakah kemaafan sehingga dosa mendedahkan akibatnya. Langsung, mereka dirasuki rasa ingin dimaafkan. Oleh Tuhan. Oleh keadaan. Oleh pasangan. Oleh hidup. Kemaafan kudus Tuhan kurniakan tidak pun menidakkan hukuman yang menyusul kemudian. Mereka diusir, dipisah ke bumi yang hening, membahasakan hukuman ini sebagai penebusan atau keinsafan. Maka kita namakan momen ini Kemaafan Pertama dalam sejarah manusia. Peristiwa-peristiwa biblical dan Quranik saya tekuni ia mengalir sebagai sumber mengilhami sikap manusia. Dari situ, kita jadi pembaca atau penulis kerana wahyunya sampai ke tangan-tangan kita yang murba. Maka kemaafan dan sastera, saya melihat ia padanan yang penting.
Kemaafan dianjurkan secara samar dalam pengkaryaan. Kalau Alexander Pope memuliakan kemaafan, saya pula senang melihat kemaafan ini harus diteropongi dari banyak penjuru; ia subjek kemanusiaan besar dengan sub-cabangnya; dalam kemaafan; kita akan menemui perihal emosi berbelah-bahagi. Ada balas-dendam. Ada penebusan. Ada taubat. Derrida meyakini bahawa kemaafan bukan suci dan mutlak; namun pada saya, jika ia suci pun, kesuciannya tidak sehala dan penuh anti-cinta ketika menuruni lorongnya. Proses memaafkan berpangkal daripada kengerian nasib dan kesalahan yang tragis. Semua gejala kemaafan kita temui dalam kitaran karya, setiap musim, setiap zaman.
Tidak sedikit karya-karya memperkatakan kemaafan, meskipun pengucapannya konvensional dan simplistik. Ia menjadi persoalan: adakah sastera tempat pengarang mendedah ukuran moral dan ingin bermaafan? Mengarang untuk memaafkan diri sendiri dan mereka yang mencemari kita. Mengarang untuk memaafkan helah takdir. Mengarang untuk dimaafkan Tuhan. Seolah kita mahu memancing sesuatu menerusi karya. Sajak-sajak yang mengusung kemaafan bagai tugu, ingin dilihat orang-orang sebagai kerja mulia. Achmed Adam dalam sajaknya; “engkau akan menulis puisi untuk mengumpan Tuhan.” Mengumpan Tuhan boleh ditafsir dengan seribu kemungkinan; barangkali pengarang ingin mengumpan keampunan dengan karya mereka yang kecil. Kerana kemaafan ialah produk penyesalan yang mendamba perhatian; sama ada perhatian jujur atau perhatian palsu. Sebagaimana kelakuan disuburi niat, begitu juga bahasa dibayangi niat. Kita boleh menegur kemaafan yang diperagakan, kerana bahasa pengarang boleh memberi klu kebanyakan masa, bahawa dia sedang ikhlas, atau berpura-pura, atau terlalu budak-budak introspeksinya.
Sajak-sajak keagamaan misalnya, wajar juga kita curigai apabila sajak dirias secara generik, imej ditekap-tiru, tiada identiti yang segar, malah tidak menjelaskan apa-apa kecuali pengulangan ungkapan yang menjemukan. Jadi, kemaafan yang bermakna itu, seharusnya terserlah dalam usaha pengucapan yang berbeza dan tersendiri. Pengarang yang ingin memaknai kemaafan, mesti payahkan diri. Cipta kerumitan. Gejolak pengarang menempuhi ancaman eksistensial atau narsisme. Mereka memuatkan kemaafan melalui sastera; adakah kerana sastera mewujudkan ruang untuk mencipta kemaafan yang tidak pernah berlaku – atau ingin berlaku? Kemaafan yang faktual seperti permohonan maaf terbuka (public apology) – antara menteri kepada marhaen – antara selebriti kepada industri – atau kemaafan yang diimaginasikan, seperti Ian McEwan, dengan novelnya, Atonement, mendirikan protagonis yang juga mendukung watak antagonis, Briony Tallis, mengangankan dosa fitnah dia lakukan kepada keluarganya suatu hari dibalas kemaafan dan diakhiri kebahagiaan, sedangkan ia tidak berlaku. Kemaafan dia angan-angankan menjadi tafsiran agung kepada pembaca tentang dosa, kepolosan, dan siapakah berhak menerimanya. Dostoyevsky bina watak-watak murung seolah enggan memburu kemaafan. Novelanya The Meek One; suami yang narsistik; malu menuding salah diri, malu merangkak menuju keampunan setelah isteri bunuh diri. Agaknya, proses kemaafan sering terperangkap dalam keangkuhan yang sukar dijinakkan.
Ini memungkinkan ada sisi lain iaitu sastera menganjalkan makna kemaafan dan menawarkan tafsiran atau interpretasi kemaafan yang baharu. Tidak bermaksud kemaafan dalam karya sastera akan menyudahkan segala perasaan amuk, dendam dan marah; saya fikir ini idealistik. Cuma saya percaya, ia bina ruang semisal makmal untuk pengarang bereksperimen meleburkan sudut-pandang tentang kemaafan yang baku. Pembaca mengalami gambaran tentang hubungan antara dendam dan maaf secara bertahap, tak terburu-buru, dan tentu sekali imaginatif. Kemaafan yang ampuh dalam pengkaryaan; ia tidak berselindung di balik bahasa yang generik. Kemaafan tulus dalam karya tidak semestinya dijelmakan dalam ucapan yang bersih. Kemaafan lebih direnungi dalam kekesatan hidup yang buruk dan tabu, menuntun kita kepada persoalan moral sekaligus. Tiada kemaafan tanpa iringan balas dendam, sama ada sebelum atau selepas tragedi. Semisal masihkah ada kemaafan selepas pembunuhan antara adik-beradik, penganiayaan emosi dan seksual; sumbang mahram; atau pasca-bunuh-diri membongkar kegelapan mangsa dan melondeh ketidaksenonohan fikiran. Mungkin ini Derrida maksudkan, dan Johan Radzi ingin lanjutkan; sebuah paradoks kemaafan. Keadaan tak termaafkan dalam hidup; dibawa ke dalam pengkaryaan untuk dimaafkan.
Kala saya menulis ini, ironinya saya lakukan untuk memaafkan sesuatu yang tidak selesai dalam hidup. Konflik kemaafan, merancang dendam; ia imaginasi yang lahir setelah kesalahan terjadi. Saya terbayangkan kemaafan yang tidak pernah wujud; seperti bagaimana kalau Adam dan Hawa diampuni dan tak terhukum. Akan bernilaikah manusia tanpa dosa dan kemaafan? Barangkali harus kita mendahului setiap peringkat dosa sebelum merasai nikmat kemaafan yang tidak terbelenggu oleh syarat dan muslihat.