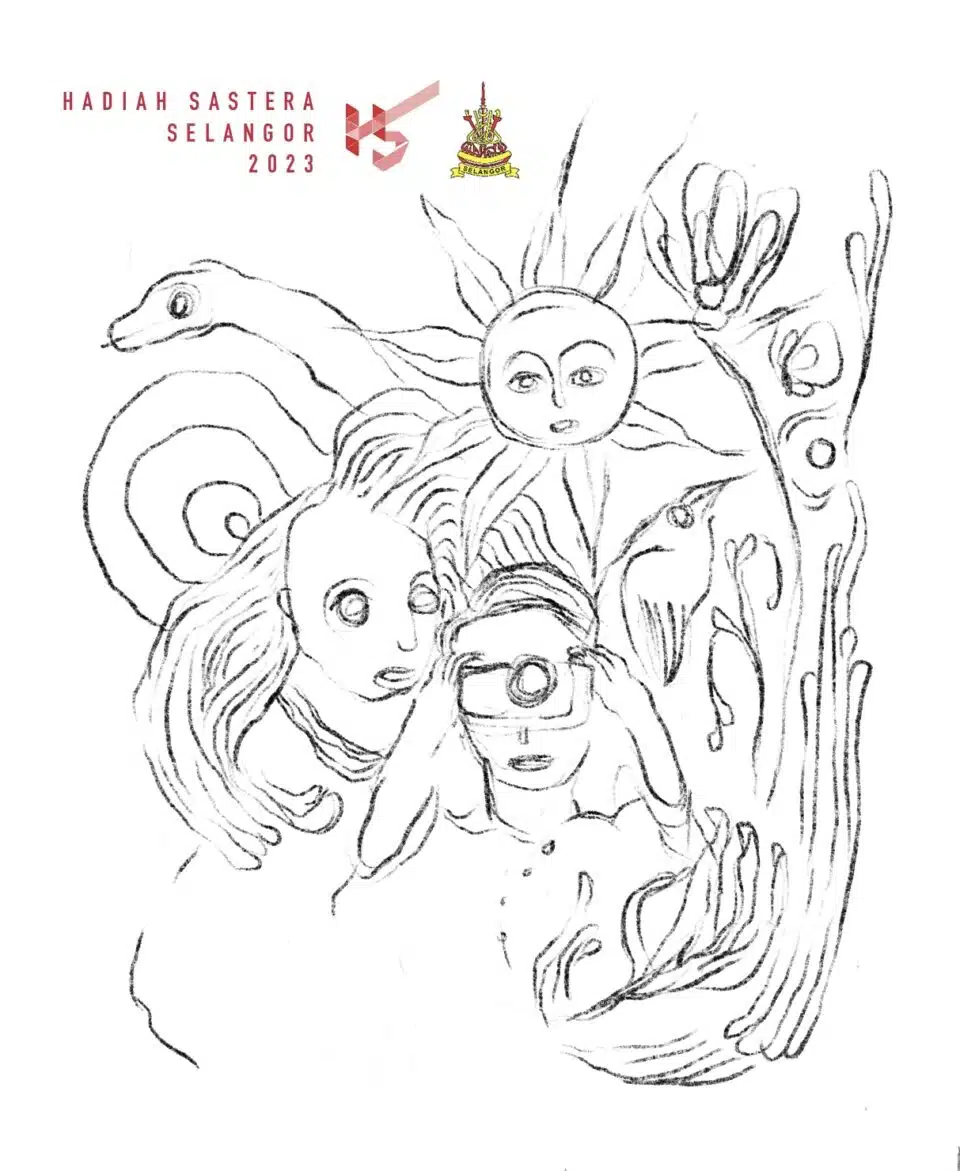Oleh Adam Taufiq Suharto
Menulis esei begini saja adalah sesuatu yang jarang saya lakukan di masa lepas, yakni menulis tentang sesuatu yang sedang saya alami via amali. Lazimnya, yang ditulis adalah sesuatu yang saya nikmati seperti filem yang ditonton atau buku yang dibaca tetapi kali ini, lain, bertentangan. Beginilah, ia bermula dengan mencari sebuah hobi yang dapat menyepak saya keluar dari rumah dek tuntutan saya sekarang menghendakkan saya berdiam di bilik (atau di pustaka atau di mana-mana) dengan membaca dan mengetik papan kekunci. Satu hari, tanpa angin, tanpa ribut, saya membeli sebuah kamera filem ‘ulang guna’ (kerana saya tak pernah memiliki kamera digital) untuk tujuan fotografi jalanan (street photography) yang waktu itu masih saya fahami dengan cetek dan sempit.
Awal mula pertama mula, saya lebih banyak terpengaruh dengan foto-foto Daniel Arnold walaupun sewaktunya, mengagumi Daido Moriyama dengan pendekatan wabi-sabinya. Yang digemari dengan Daniel Arnold adalah keanehan manusia-manusia dalam fotonya serta gayanya yang bersahaja lagikan tidak mempedulikan orang dan ini sedikit sebanyak mempengaruhi saya untuk menyuluh flash ketika berfotografi. Maka sebab itu, saya menyusuri Bukit Bintang kerana menurut saya manusia-manusia New York seperti dalam foto-foto Daniel Arnold mungkin wujud di Bukit Bintang. Begitupun, ini bukan bererti saya menganggap Bukit Bintang itu ‘New York’, tetapi kerana ragam dan citra manusia di Bukit Bintang itu adalah pelbagai (yang pada waktu itu saya fikir bolehlah dapat apa yang Daniel Arnold dapat).
Masa berlalu dengan pantas pada saat saya dilamun fotografi jalanan dan setelah sebulan dua, saya mulai sedar dan tercerah bahawa hanya Daniel Arnold yang boleh mengambil foto seperti Daniel Arnold. Maka, datanglah kesedaran untuk membumikan foto-foto saya supaya ia merakam manusia-manusia Kuala Lumpur bukan New York atau yang lebih tepat, mencari ‘saya’ di dalam foto-foto saya dan bukan mencari ‘Daniel Arnold’ di dalam foto-foto saya.
Namun, saya dalam keadaan sedar bahawa tidak mungkin foto seorang fotowan akan sama dengan seorang fotowan yang lain. Sebab itu wujudnya kata-kata, ‘setiap foto adalah potret diri (self-portrait)’. Gambar-gambar yang kita ambil itu sebenarnya menggambar diri kita. Kita tak akan dapat menangkap foto anjing Daido Moriyama kerana ‘anjing’ yang akan kita temukan adalah ‘anjing kita sendiri’, bukan ‘anjing Moriyama’. Maka sebab itu setelah kita mengambil gambar, dan melihatnya satu persatu, kita akan dapat membuat penilaian sendiri terhadap diri kita. Makanya daya percaya kita sebenarnya keluar mengambil gambar bukan untuk mengenal apa yang di luar sebaliknya untuk kenal apa yang ada di dalam diri, baik di alam fikir mahupun di alam rasa.
Tentang hal lain, kadang-kala saya sendiri terfikir, apa yang menyebabkan fotografi jalanan begitu ‘kerasukan’ kepada saya? Mengapa fotografi jalanan ini berupaya menanamkan obsesi baharu dan semangat yang berkorbar seusai saya jatuh cinta padanya? Dan ini seakan-akan terjawab apabila suatu hari saya menonton sebuah dokupen (dokumentari pendek) tentang Aaron Berger, fotowan jalanan New York, yang pernah mentamsilkan fotografi jalanan sebagai satu bentuk sukan; mungkin didorong latar belakangnya sebagai bekas atlet bola sepak. Maka, dia merasa ‘terasuk’ dengannya dek rasa seolah-olah dia sedang berolahraga.
Saya fikir jawapan Aaron Berger hampir menjawab persoalan saya biarpun tidak seluruhnya. Kemudian, saya terjumpa kata-kata yang Alec Soth yang seolah-olah memberikan jawapan penuh terhadap sebab-musabab tindakan berfotografi jalanan begitu ‘merasuk’ saya. Alec Soth yang juga ahli Magnum Photos mengatakan, “I fell in love with the process of taking pictures, with wandering around finding things. To me it feels like a kind of performance. The picture is a document of that performance.”
Hal ini menyedarkan saya kepada dua perkara; pertama, mungkin kerana itu saya begitu suka menyaksikan gerak-kerja dan lagak-latah fotowan jalanan dalam video-video belakang tabir atau dokupen-dokupen mereka kerana video-video itu sebenarnya adalah satu bentuk persembahan, persembahan mereka dalam berfotografi jalanan. Misalnya, bagaimana Bruce Gilden menyuluh flash berdepan muka dengan subjek-subjeknya atau kronfrontasi-negosiasi Trevor Wisecup selepas dia mengejut-hendap subjek-subjeknya dengan flash atau setenang mana Martin Parr mendapatkan syot-syotnya atau seaneh mana Garry Winogrand mengemudi kamera yang kekadang mendatangkan seribu satu hairan.
Kedua, ia menjelaskan mengapa saya begitu ‘terasuk’ dengan fotografi jalanan adalah kerana tindakan itu sendiri satu bentuk ‘seni’, ‘persembahan’ bak kata Alec Soth tadi. Ia menuntut saya mencari helah dan jalan dalam merakam sesuatu foto yang diigin. Kadang kala ia menuntut berani untuk menangkap gambar dengan dekat. Sudah tentu itu adalah antara hal yang mencabar kerana untuk ada keberanian mendekatkan diri kepada subjek dan mengetik gambar, ia juga menuntut persediaan dengan seribu satu kemungkinan sama ada di konfrontasi mahupun diperintah tunjuk gambar atau diancam memadam gambar. Maka, ‘ketidaknampakkan’ (invisibility) seorang fotowan adalah hal yang utama untuk dikawal dan diuruskan.
Melakukan fotografi jalanan juga menjadikan kita pesiar atau kata orang Perancis, seorang flaneur. Kita boleh lihat watak atau naratif flaneur ini dalam sinema Perancis seperti dalam filem Cleo: 5 to 7 (1962) dan The 400 Blows (1959) yang karakter-karakternya sering berlegar-legar dan berpeleseran sekitar kota. Menjadi seorang fotowan jalanan juga bukan hanya menjadikan kita sebagai seorang flaneur yang berjalan tanpa arah (biarpun masih ada tujuan mengetik foto), tetapi turut menjadikan kita sebagai seorang pemerhati masyarakat. Ia juga membantu mengubah pandangan sarwa kita terhadap orang-orang di jalanan yang datang daripada pelbagai latar dan kelas yang mungkin dahulu ada ‘penjarakan’ antara kita dan mereka. Ia membumikan dan memanusiakan.
Pada akhirnya, saya ingin menutup penulisan ini dengan sebuah penegasan yang boleh jadi benar dan tidak benar yakni saya berpandangan fotografi jalanan sebenarnya agak spiritual. Spiritual bukan dalam bentuk ia adalah sebuah ritual keagamaan tetapi dalam erti kata, kita turun ke jalan setiap minggu (atau mungkin setiap hari?), dalam keadaan ‘menjangka apa yang tidak terjangka’ dan kita tidak sepenuhnya pasti apa yang bakal kita perolehi. Separuh sedar dan separuh berserah.
Tindak tanduk ini tidak sama seperti seorang seniman membikin filem (secara konvensional), melukis atau menulis yang mana dalam keadaan sedar mereka mengawal sebuah ‘pembikinan’ sementara fotografi jalanan bukan (sepenuhnya) satu bentuk ‘pembikinan’ kerana terhadnya proses imitasi. Fotografi jalanan adalah satu bentuk ‘penyerahan’ yang mana kita sebenarnya membenarkan diri kita melalui proses mempotret dengan ketentuan nasib dan takdir yang membawakan kita kepada cahaya, subjek, warna yang berada di luar kawalan kita dan… bukankah hidup sebenarnya begitu? Barangkali, inilah yang dimaksudkan William Klien sebagai, “…separuh daripada apa yang saya lakukan adalah nasib.”