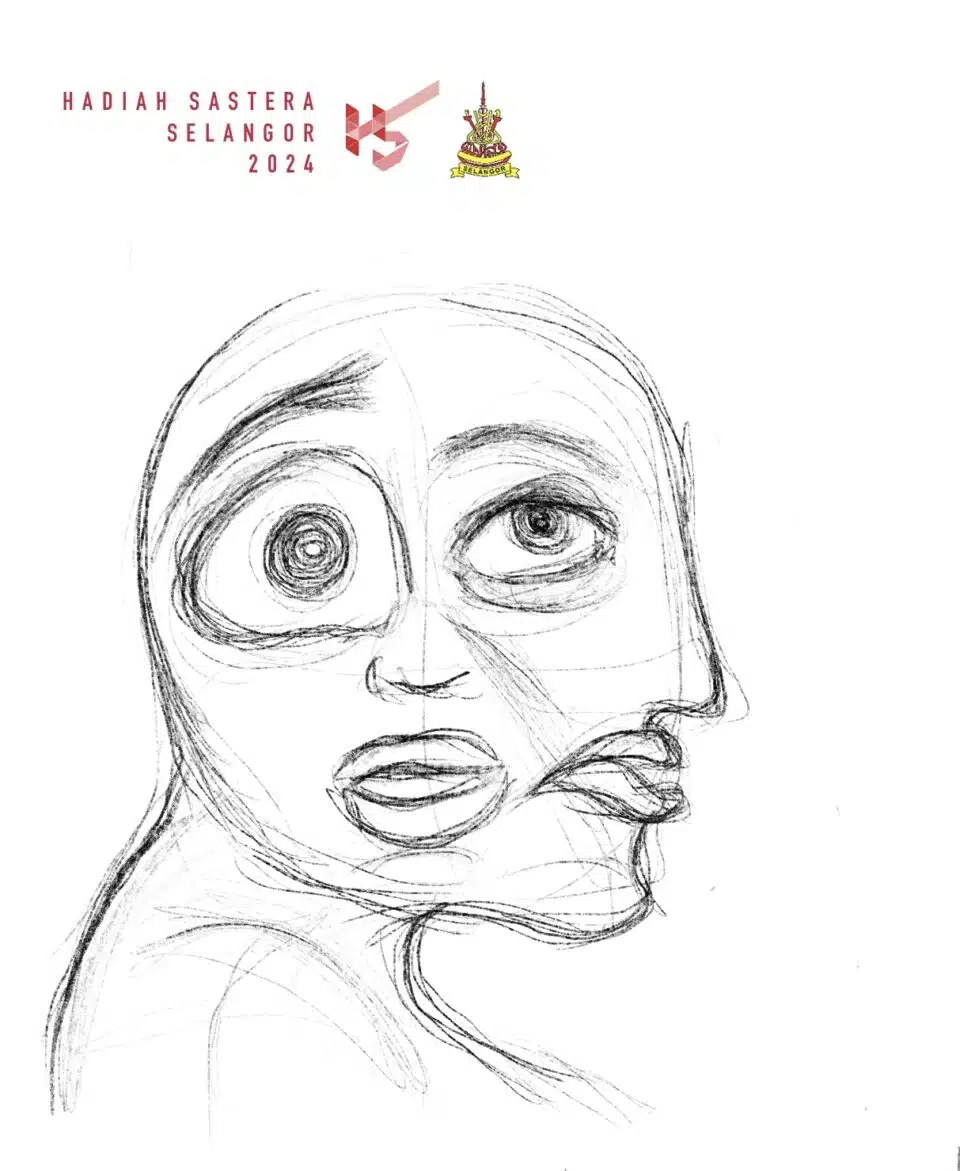Oleh Ruhaini Matdarin
Aku ingin membuang suamiku di hutan sebelum jiran kami, seorang pegawai polis balik dari bekerja pukul enam petang nanti. Aku mempunyai masa sepuluh jam untuk menjayakan rancangan. Baru pukul lapan pagi. Dinihari tadi aku terjaga kerana dengkurannya yang seperti tikus berdecit. Menjengkelkan. Meskipun mulutnya tertutup aku dapat menghidu nafasnya yang berbau ammonia kerana sudah bertahun-tahun melawan Diabetes Mellitus Tahap Dua. Dari kerusi malas tempat aku menyandarkan keresahanku di tepi tingkap kamar, kau boleh melihat dia tidur nyenyak persis ikan buntal terdampar.
Inilah rencananya; sebentar lagi aku akan bancuh kopi hangat seperti pagi-pagi hari lain untuknya. Selepas setengah jam dia akan menerima sarapannya; roti bakar, telur dua biji setengah masak dan satu per empat epal hijau. Dia senang menikmati makan pagi ringan di balkoni lantai dua, sambil membaca berita di portal. Dia mungkin menjerit meminta dibawakan segelas air kosong. Pada waktu itulah aku akan membubuh Eszopiclone ke dalam minumannya.
Dia cenderung jatuh tidur kurang daripada sejam setelah mengambil ubat-ubatan. Dia mungkin tidak sempat menikmati makan tengahari. Aku akan menitipkan kudapan dalam beg galas apabila meninggalkannya di hutan nanti. Dia pastinya tidak menghadapi kesukaran menjalani hidup dalam hutan berkat menonton Animal Planet dan peminat tegar National Geographic.
Untuk bertemu jalan keluar adalah tidak mungkin kerana kaki kirinya sakit. Sebab itulah dia banyak menghabiskan waktu di kerusi malas depan televisyen yang dibisukan kerana ingin fokus membaca buku. Kerana ciri khas dirinya itu dia berfikir dia istimewa macam Donald Trump. Menentukan apa yang patut dan tidak patut aku lakukan di ruang aku sendiri. Dia tidak suka aku membuat bising di dapur semasa dia membaca buku di depan televisyen yang bisu. Tidak lama lagi dia akan berebut kebebasan dengan binatang liar.
Kami tidak dikurniakan anak. Aku sempat membela anak adikku sejak usianya dua tahun. Dia pulang ke pangkuan ibu bapanya pada usianya 16 tahun. Aku tidak sedih ditinggalkan. Tempat tinggalnya hanya di belakang rumahku. Setiap masa dia akan datang berziarah, atau aku pergi bertemunya. Satu-satunya hal yang membuat aku kecewa kerana ketiadaannya memberi ruang kosong kepadaku untuk bertumpu kepada suamiku. Menjaganya macam menjaga bayi.
Kami sering kehabisan modal untuk berbual-bual. Memperkatakan topik kecil seperti masinnya atau pedasnya lauk-pauk kumasak yang berkesudahan dia membantai betapa teruknya kemampuanku memasak sesuai selera dan kemampuannya makan setelah berpantang makan sejak dua belas tahun lalu. Aku melawannya dengan isu nafas busuknya atau betapa tidak berfungsinya dia setelah jatuh sakit akibat tidak menjaga pemakanan serta faktor genetik.
“Kalau firaun masih hidup, dia pun tak sudi mengambil kau jadi pengikutnya.”
“Kau boleh perli aku sepuas hati. Tapi jangan kau lupa, syurga isteri ada pada suaminya.”
Anehnya, perkelahian remeh-remeh seperti itu berhasil menyelamatkan bibit-bibit parak yang sekian lama tertangguh antara kami. Sudah hampir sedekad cerita kami ingin berpisah tetapi tidak kunjung tiba perpisahan yang dimaksudkan. Sehingga kami menjadi tua, sakit, nyanyuk dan segalanya menjadi terlambat.
Penyakit lupa yang aku deritai sejak pertengahan usia 40-an, semakin teruk. Doktor menasihati agar aku berhenti bekerja setelah aku didiagnosis mengidap demensia tahap awal. Sudah empat biji kuali aku hanguskan. Aku tidak ingat aku telah menyalakan api. Aku juga lupa apa yang ingin kumasak. Banyak kali aku masuk dalam kereta, menghidupkan enjin tetapi kemudian keluar tergesa-gesa kembali ke rumah. Kereta itu tersadai di bengkel setelah beberapa kali aku membiarkannya hidup tanpa dipandu selama berjam-jam sehingga enjinnya rosak.
Pencen suamiku sebagai mantan pengarah sebuah jabatan sektor kerajaan, mujurlah cukup menanggung kos sara hidup kami yang tidak mahal. Aku sudah tidak larat mencari pembantu rumah yang tahan melayani perangai cerewet suamiku. Dia seolah-olah perfectionist tetapi cenderung kepada OCD. Dia tidak mahu tangan pembantu rumah membersihkan punggungnya setelah malaikat maut mencabut nyawanya. Atau, mati di katil hospital menjalani rawatan menyakitkan.
“Jalan ke kubur tidak mengenal hari libur,” aku menenangkannya sebab aku mengerti insulin dalam tubuhnya naik mencanak usai makan siang. “Kita boleh tentukan cara kita jalani hidup tapi kita tak boleh pilih cara untuk mati.”
“Jangan acah-acah jadi macam Najwa Shihab,” dia memerli aku yang berusaha membuatnya tenang.
“Lebih baik kau diam.”
Akan tetapi, bukan itu penyebabnya aku mahu membuangnya di hutan. Melainkan kerana dia memburuk-burukkan aku di sebuah laman mencari jodoh. Aku menangkapnya bersembang dengan gadis muda. Dia mengaku duda. Dia mereka-reka cerita kematianku; semasa merayap-rayap di hutan aku dibaham binatang buas. Ditemui oleh pasukan penyelamat tanpa dapat dikenali melainkan setelah ujian DNA dilakukan. Tragis sungguh, kan?
Sebab itu aku nekad membuangnya di hutan. Jikalau kau berada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Menyerkup kepalanya dengan baldi lalu menggendang baldi itu dengan batang penyapu? Atau, pasrah seperti wanita Timur yang menganggap semuanya ujian dari langit?
Masalah terbesar yang aku hadapi ialah bagaimana membawanya turun ke lantai bawah, memasukkan dalam kenderaan dan menariknya sejauh belasan kilometer dari jalan raya besar di simpang jalan pekan, menuju ke hutan. Kau lihat saiz tubuhnya? Sekurang-kurangnya memerlukan enam atau tujuh orang lelaki dewasa untuk menggerakkannya. Kau bayangkan saja mengusung jenazah di atas tandu.
Jiran kami si pegawai polis berteriak di luar halaman sebelah, menyapa aku yang menyandarkan tubuh ke bibir jendela, yang sebentar tadi aku buka kacanya luas-luas. Pemuda itu melambai. Tanpa aku tanya, dia beritahu tentang ‘diriku’ sudah ditemui di hutan, mungkin tersesat semasa berjalan-jalan ambil angin. Aku tersentak.
“Perlu post mortem,” Aku rasa aneh kerana dia tidak memandang aku. Seolah-olah dia bercakap dengan seseorang di belakangku. “Abang harus ke hospital untuk pengecaman jenazah.”
Aku menoleh suamiku yang merenung ke luar halaman. Matanya basah.
“Bukan dengan cara ini kita harus berpisah,” suamiku berbisik. “Tapi bukankah jalan ke kubur tak mengenal hari libur?”