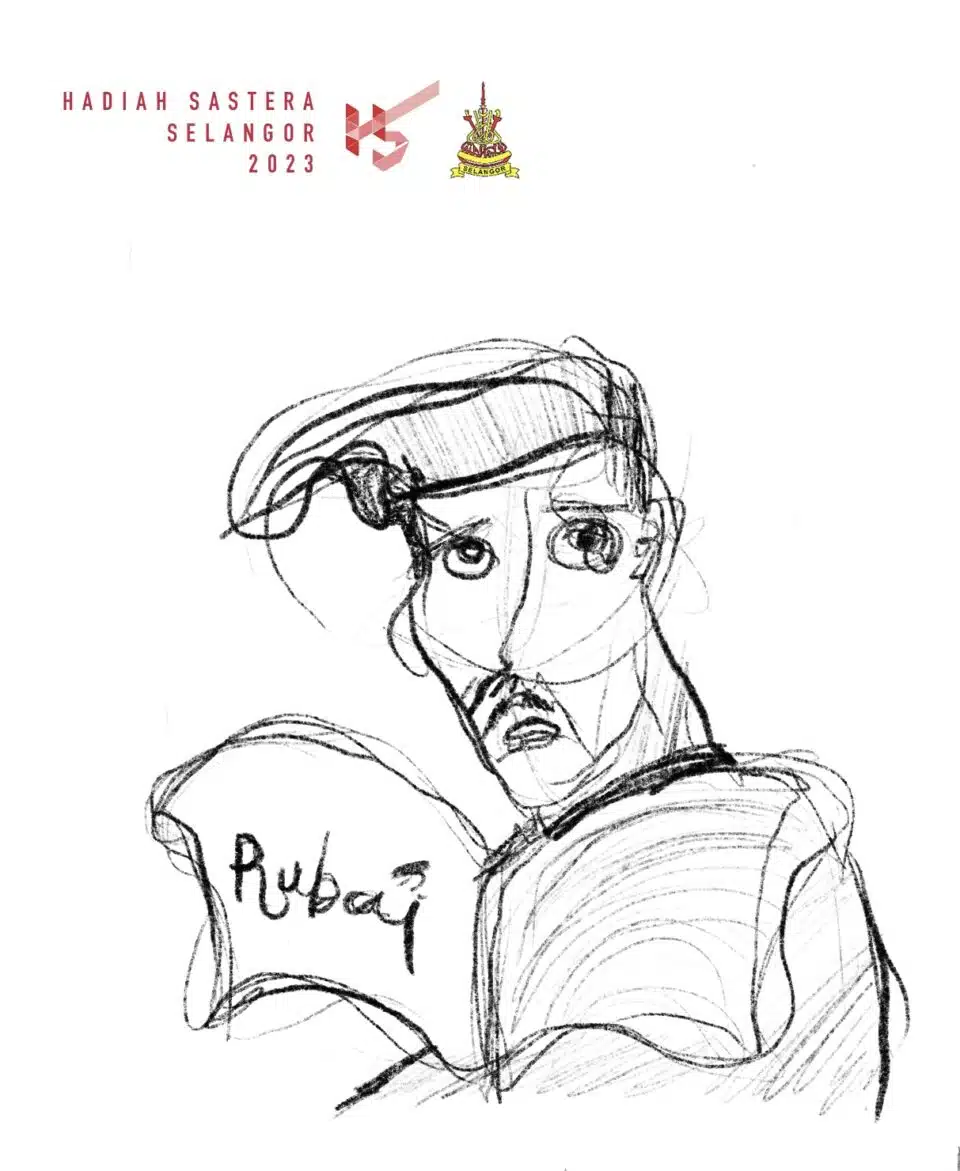Syarah terhadap Ruba’i karya Hamzah Fansuri yang dilakukan oleh Syeikh Shamsuddin ibn Abdullah al-Sumatrani barangkali antara karya kritikan puisi terawal yang pernah dihasilkan di Nusantara. Esei karangan Syeikh Shamsuddin tersebut telah diabadikan oleh Almarhum Profesor A. Hasjmy dalam bukunya Ruba‘i Hamzah Fansuri (1976). Syeikh Shamsuddin, ulama kelahiran Samudra Pase, Aceh ini merupakan anak murid terkenal Syeikh Hamzah Fansuri.
Dengan banyaknya sajak semberono dan ‘asal boleh’ yang dihasilkan hari ini, sepatutnya merancakkan lagi dunia kritikan sastera kita. Tapi peliknya yang terjadi adalah sebaliknya, dunia kritikan kita menjadi amat lesu, malah begitu sepi. Jarang sasterawan muda kita mahu menulis kritikan terhadap karya penulis lain. Esei kritikan tulisan sarjana kita terhadap karya sastera terbaru yang terbit dalam negara sesekali muncul dalam majalah dan juga akhbar. Lebih malang lagi yang paling jarang dikritik di sela-sela antara esei kritikan yang kadang-kadang muncul itu adalah buku sajak dan juga sajak eceran yang berterabur dalam pelbagai penerbitan. Dunia kritikan menjadi sunyi sepi dan senyap sedu itu pun akibat daripada sikap penulis kita sendiri sebenarnya. Maka, berhentilah menyalahkan orang lain sebelum cuba menghasilkan esei kritikan dan dalam masa yang sama menulis sajak yang sebenar.
Esei kritikan yang khusus memperkatakan sesebuah karya ini tentu saja akan membantu penulis tersebut memperbaiki karyanya agar menjadi lebih baik pada masa hadapan. Apabila rancaknya penulisan esei kritikan terhadap karya-karya yang dihasilkan tentu saja akan mengurangkan jumlah sajak-sajak mengarut dan tidak berkualiti. Ketika negara kita memasuki tahun 2020 yang lalu iaitu tahun penting yang telah kita nanti sekian lama untuk melihat negara ini menjadi sebuah negara maju, masih ramai menulis sajak yang kualitinya tertinggal 20 tahun, atau mungkin 50 tahun ke belakang. Sepatutnya sajak kita juga perlu berkualiti dan mampu mendepani zaman setanding dengan kemajuan teknologi hari ini.
Kita menulis bahasa yang pelik-pelik dan perlambangan yang bukan-bukan hanya kerana ingin menampakkan karya itu sebagai sebuah sajak agar kita saja dapat memahaminya, sedangkan orang lain terkial-kial membacanya. Berhari-hari masa diambil untuk menghadam dan memahaminya. Itulah sajak bagi kita. Jadi bagaimana keadaan orang awam yang membaca karya sastera?
Sajak Rendra mudah, dan sajak Joko Pinurbo juga mudah. Malah karya Sapardi Djoko Damono juga lebih senang difahami berbanding sajak-sajak kebanyakan penulis Malaysia yang karyanya disiarkan dalam ruangan puisi dalam majalah dan akhbar kita sekarang. Sukar difahami bukan kerana sajak itu bagus dan berkualiti tetapi kerana penyair itu asyik dengan bahasa dan frasa pelik ciptaannya sendiri. Itulah masalah penulis kita, apabila menulis sajak mestilah dengan bahasa yang berbunga-bunga dan bombastik sahaja. Bahasa biasa dan mudah tidak boleh. Sajak itu perlu sukar difahami dan tidak dapat dihadam dengan hanya sekali baca. Permainan bahasanya keterlaluan, berlebih-lebihan.
Perhatikan sajak-sajak Chairil Anwar dan Wiji Thukul. Walaupun dua penyair Indonesia yang meninggal dunia ketika usia muda ini menulis sajak-sajak perlawanan, namun karya mereka memiliki kehalusan dan keindahan seni ciptaannya yang tersendiri. Memang kita tidak menafikan kekuatan karya Chairil berbanding Wiji, namun sajak-sajak Wiji Thukul tetap punya kekuatannya tersendiri, malah yang setanding dengan sajak perlawanan Chairil juga ada.
Sajak Zurinah Hassan pun mudah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan kita berfikir dan minda kita berfungsi, bergerak dan menaakul sesuatu isu atau perkara apabila membaca sajak-sajak Zurinah. Dia tidak memaksa kita. Dia tidak memeningkan kita dengan bahasanya yang pelik-pelik.
Ada cerita dan kisah-kisah yang menarik dalam karya Hilmi Rindu walaupun bahasanya biasa dan sajaknya mudah. Gaya naratif dan berterus terang pula terdapat dalam sajak-sajak Azman Hussin, namun karyanya masih berseni dan tidaklah terlalu polos serta prosaik seperti karya Leo AWS. Namun sayang Azman tidak lagi prolifik menulis sajak persis Leo AWS yang menjadikan karya sastera itulah diari hidupnya. Sajak dengan gaya naratif ini juga menarik jika tidak begitu keterlaluan prosaiknya. Sajak-sajak ciptaan Rosli K. Matari, Fahd Razy, Adinata Gus dan Abdullah Hussaini juga mudah dihadam oleh kebanyakan pembaca.
Ali Ahmad dalam bukunya Asas Menganalisa Sajak (1971) sejak lebih setengah abad lalu telah pun menegur perihal kelemahan sajak-sajak Melayu iaitu katanya karya yang mempunyai nilai yang lengkap daripada sudut isi, kesatuan fikiran, emosi dan pemilihan kata yang tepat serta bersesuaian amat sukar ditemui pada zamannya kerana masih ramai penyair menggunakan kata basi yang klise dan diulang-ulang frasa yang sama sejak sekian lama. Hendakkah kita digelar sasterawan kolot yang tertinggal lebih setengah kurun ke belakang jika pada tahun 2023 di abad baru ini pun masih jumud mengulang-ulang kata basi yang sama dalam karya sastera yang dihasilkan?
Kelemahan sajak-sajak terkini penyair kita ialah bahasanya tidak konkrit seperti sebuah sajak dan ceritanya tidak kukuh sebagai sebuah karya seni. Itulah identiti sajak-sajak penyair kita mutakhir ini. Bahasanya seperti cuba bermain dengan ritma dan irama, tetapi terlalu dibuat-buat, dan ideanya kontang dan keanak-anakan. Malah kias dan ibaratnya seringkali tidak bertepatan dan kurang sesuai. Personafikasi dan perlambangannya selalu pula mengelirukan. Semakin diulang membacanya kita semakin bingung. Penulis kita tersilap dalam mengukur kefahaman pembaca dengan beranggapan ‘semakin sukar sesebuah sajak itu difahami pembaca maka semakin berjayalah sesebuah sajak itu’ di persada kesusasteraan. Berhentilah menulis “angin sepoi-sepoi bahasa”, “melabuhkan punggung”, “ibu adalah ratu hatiku”, “ombak menghempas pantai” dan “daun-daun melambai” dalam sajak, dalam cerpen. Ia sudah terlalu streotaip untuk diulang-ulang.
Jangan nanti orang memperlekehkan arena sastera negara ini hanya kerana karya kita yang buruk. Apalah gunanya kita menjadi penulis jika tidak mahu berpijak di bumi yang nyata, realiti kehidupan sebenar. Bukankah sajak itu sendiri kandungannya perlu berbicara perihal semasa dan dunia hari ini? Kita perlu menulis berkenaan apa yang terjadi sekarang. Tapi peliknya penyair masih berada dalam dunianya yang peribadi; terpesona dengan bahasa ciptaan sendiri dan leka terperosok ke dalam lenggok bahasa dan muzik bunyi dalam sajak sahaja. Jarang kita temui sajak-sajak penyair kita berbicara tentang situasi sukar kehidupan rakyat bawahan hari ini dan keadaan semasa masyarakat sekarang.
Dunia puisi kita sebetulnya sedang ketandusan sajak yang sebenar. Yang ada cuma luahan perasaan dengan longgokan kata-kata klise yang membosankan. Lebih seronok membaca pantun lama dan syair orang tua-tua kalau sajak yang diharapkan tinggal hanya frasa bunga-bunga yang kosong makna, ungkapan klise yang tidak berarah dan permainan bahasa yang berlebih-lebihan sahaja!