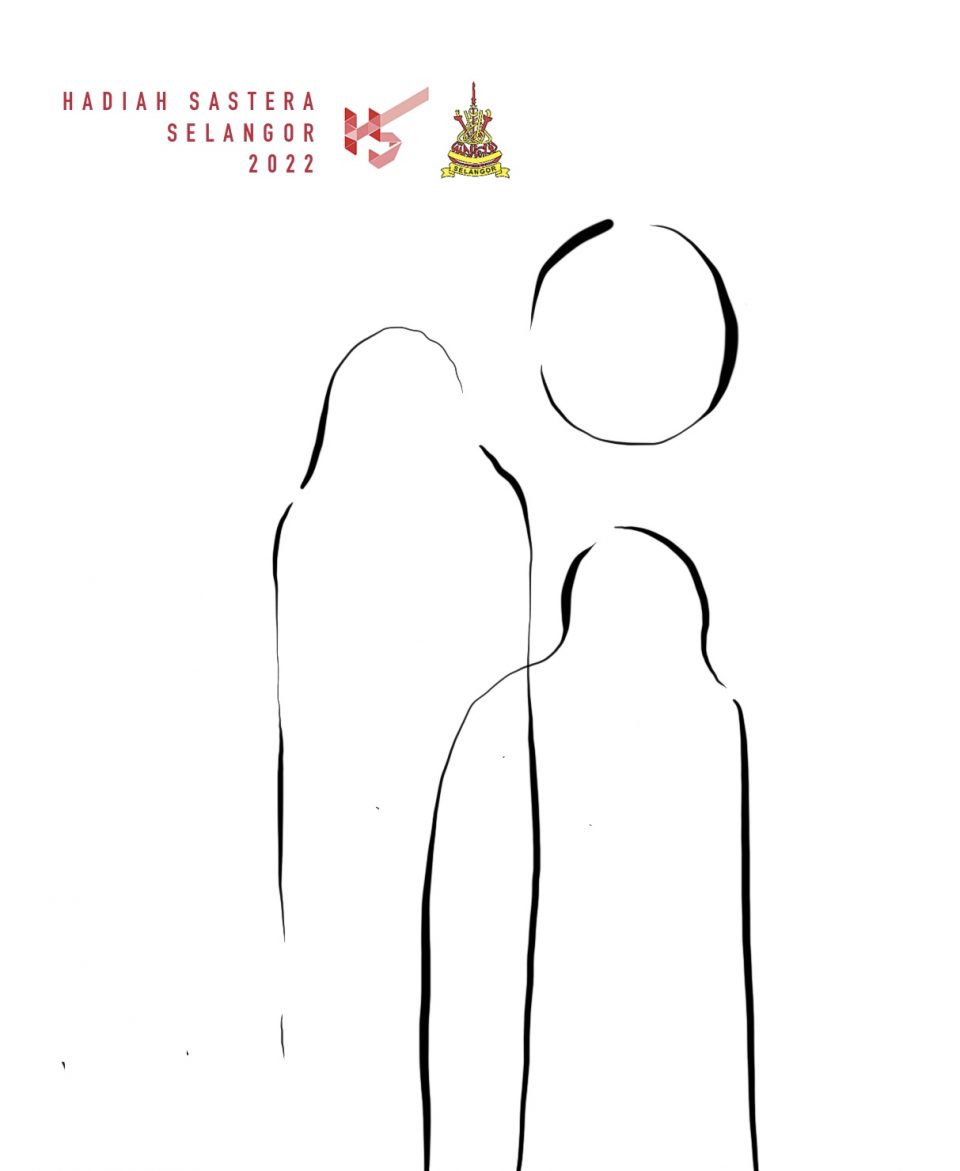Oleh Qurratul ‘Ain
(Ulasan enam sajak Syaheeda Hamdani)
Kadang-kadang, kita ambil warna biru dengan begitu mudah. Itu yang terbersit sebagai pendapat apabila aku membaca buku puisi sulungmu, Sepasang Nila di Bahu. Ia mengalirkan reaksi yang perlahan, kerana biru ialah warna yang tidak deras. Sebaliknya, ia warna yang banyak bersaudara dengan perasaan pilu. Warna yang mengubati. Warna yang membumi. Warna yang melaut. Mungkin kau terlalu sukakan biru, aku merasakan biru memperlahankan sajak-sajakmu. Ada enam antara puluhan sajakmu yang aku fikir, menjadi beberapa pintu istimewa untuk menjenguk peribadimu.
Kuulangi juga pakai Sepasang Nila yang pernah melekat pada bahumu. Lama juga aku biarkan ia tersangkut di belakang pintu, berdiam bersama jaket denim dan seluar lusuh. Sajak-sajakmu pelepah yang tidak pernah gugur. Kau berani melekatkan setiap satu. Kupakai dan terasa ringan pula. Ia melayahkan aku ke mana-mana kota yang kaugeluti. Semuanya cenderung biru walaupun sesekali ada ikutan kuning nangka mentari melengkung. Berat hendak aku teliti warna yang pernah tidak dinamai orang-orang Yunani. Biru pernah tidak wujud dalam kamus penyair Athens. Agak ganjil juga dan aku terbayang bagaimana dramatiknya ragam filasuf Yunani apabila cuba menjunjung langit dan memikul laut? Biru membunting warnanya sendiri dan menawarkan keturunan spektrum yang tidak terduga. Biru lazuli. Biru turquoise. Tapi kau memilih biru nila untuk menyuntik dalam perenungan – kukira, seperti suatu tanggung jawab yang kupilih sendiri, memperagakan kepada mereka, pembaca-pembacamu yang tak bernama, tak berwajah.
Banyak daerah dalam sajak-sajak kamu perlu dibedah, disiasati dengan meminjam horizon fikiran seorang kartografer. Tapi aku tahu, manusia cuma mampu menyimpan beberapa cinta yang terbatas pada sesetengah tempat sahaja. Kita tidak akan suka segala ruang yang ada, walaupun pernah bersetubuh dengan suasana di suatu daerah itu. Mula-mula aku tiba di dimensi sajakmu, aku di Pintu Pertama. Dibaliknya ada pegun Tubuh Kota. Segalanya terbelah menjadi dua.
cekung mentari bercermin. tak berbayang / mentari satu: terang seperti kelmarin / cahayanya berwarna nangka. /mentari dua: kelabu mencair seperti asbak rokok pengembara.
Lopak di aspal, ada takungan hujan menjadi cermin untuk melihat sisi lain. Keinginan untuk memahami lapis kota. Kerana kita selalu atau cuba percaya, bahawa sebuah kota dibina atas kota purba yang terdahulu. Kota diganti kota. Begitu apa yang Tubuh Kotamu sedang bercerita, di situ terbagi dua; saling bercermin, saling berganti suasana. Tidak terkecuali dirimu sendiri – dirimu seorang lagi dalam remang biru – menelan pil antidepresan. Ia umpama suara maut yang kejauhan. Ternyata, merenungi kota ialah cara kau melihat lubuk pedih kesedihanmu.
Kemudian suaramu menuntunku ke belakang lorong di Tubuh Kota, katamu ada Pintu baharu yang mesti aku masuki. Dengan teragak-agak, aku pusing tombol. Rupa-rupanya aku terjunam dalam Solitud yang kau petakan. Ada banyak lingkaran kau sediakan. Lingkar dalam lingkar. Bergema di sini – dalam raungan seribu:
Solitud adalah / Sakit kepala sedang sakit kepala dan / Rindu yang sedang merindui rindu, adalah / Kesunyian paling bingit pernah kaudengar / lagu sedang putus cinta, dan / pohon-pohon tak kilas warna
Aku menemui lingkaran yang tak berhenti mengejar hujung ekornya. Apakah yang kaulalui, penyair? Solitud terperangkap dalam solitud. Aku juga, seperti mangsa yang tidak bersalah, ikut terpaut dalam pemetaan ini. Solitud yang membiru, lama-lama makin mengembang. Tiba-tiba, aku dihentak oleh tangan-tangan ghaib ke dinding. Aku dimasukkan ke dalam sebuah Sumpahan yang kaucipta. Ia sangat gelap, hanya kudengar kau sungguh terkumat-kamit. Kausulam ungkapan yang menyesakkan:
resah dalam kepala/zikirgagak kusumpah semalam/lenyap di luar rumah/mencucur darahnya di jalan/hari ini
(Baris ini, aku merasakan sayap-sayap gagak mengelilingiku, hanyir darah mengalir dari paruh-paruh mereka berbau sayup-sayup. Zikir mereka yang sepilu manusia)
resah dalam kepala/ngiaujantan kusumpah semalam/lenyap di kotak jendela/hanya ada bulubulu di langsir/hari ini
(Aku terbersin apabila angin menolak langsir menampar mukaku – bulubulu seekor kucing domestik atau Bastet yang dipuja?)
Resah-resah dalam kepalamu membising sampai dinding di belakangku merekah. Dan tersimbah lampu yang tidak kukenal. Kutoleh dan akhirnya, terlihat sosok dirimu. Di dalam bilik pastel. Kau sedang berbual dengan seseorang, dia pula membelakangi. Tapi aku, seperti perisik, mengintip dengar perbualan Perbualan Malam tentang Tuhan antara kamu berdua. Suara kalian yang penuh pengharapan dan berlagu gnostik;
ingatlah bahwa tuhan ada dua: satu mencipta manusia/satu lagi dicipta manusia/kalau kaupilih untuk sembah tuhan yang kaucipta/aku harap dialah yang menciptamu.
Mendengar ini, aku meneka-neka siapa Tuhan dalam perbualanmu, atau siapa Tuhan dalam peganganmu. Kufikir, manusia mencipta Tuhan sendiri kerana mereka cemburu dan merasa kelompongan. Kalau sesiapapun memilih untuk menyembah ciptaannya, aku berbagi harapan sama sepertimu. Dan dalam perbualan itu, kau berdoa;
aku memohon sebuah telaga tak berusia/ dan tuhan kurniakan airmatamu
Nampaknya, kesedihan bagimu adalah air yang mengisi telaga. Buat cuci diri dan nubari. Perbualanmu semakin malap dan dinding merekah tadi kembali digam rapat. Suasana berubah cerah dan teramat terang. Kupandang sekitar, semua memutih dan kemudian membiru semula. Kudengar suaramu lagi. Kau kata kita sedang berada di syurga. Benarkah? Tapi sekitarku seperti syurga yang sintetik, buatan renungan seorang penyair. Pohon khuldi menjelma satu per satu, dari benih hingga rerantingnya. Dan begitu, kaukata Di Syurga – bahawa;
selain khuldi, buah dadamu haram kupetik.
Mungkinkah kerana ia syurga yang terbelenggu dalam fikiran penyair, segalanya haram dan terbatas? Lihat, kita berdua seakan telanjang tetapi sajak kecilmu ini menjadi daun-daun yang melebar, menutupi buah dada kita. Daun-daun ini bertukar sebagai Perihal Doa yang kaugugurkan:
daun-daun liar / akhirnya memilih untuk kuning / tangan-tangan nakal / akhirnya memilih untuk katup
(daun-daun dalam sajakmu, merendah mengatup kita. Baris-barismu menguning, mengering di kaki kita)
lagu-lagu gelangkaki / akhirnya diganti loceng kuil / gincubibir mentari / akhirnya diganti kucupmesra bumi
(kita, turun ke bumi semula, di luar sajak-sajakmu yang menitis bagai nila dalam susu sebelanga; susu dari buah dada kita, susu dari sungai sana).
Akhirnya aku tiba di Pintu ketujuh, iaitu aku yang berada di dalam bilikku, membaca Nilamu. Setelah enam Pintu biru, warna-warna lain mengikuti menjadi kepengaranganmu, penyairku. Ia belahan-belahan dirimu yang terhiris oleh pengalaman dan penghayatan, aku percaya begitu. Mungkin setelah mengenali bagaimana birunya dirimu, kau akan mula beralih warna. Ingin aku pinjam matamu, penyair, tapi rabun kita tidak sama. Aku masih merangkak melihat apa yang kaulihat. Buku ini, sedang membesar. Ia menunggu untuk masuk ke halaman seterusnya.
Moga-moga kau dapat menelurkan lebih banyak warna dalam bahasamu.